KETIKA KEKUASAAN TAK MAU PERGI
Baca Juga
Panggung kekuasaan itu hangat. Setiap langkah terasa penting, setiap ucapan dicatat, dan setiap keputusan membawa dampak besar. Maka tak heran bila banyak orang sulit beranjak ketika masa jabatannya selesai. Ada semacam magnet psikologis yang menahan mereka untuk tetap berada di titik pusat, walau sebetulnya panggung telah berubah. Begitu lampu sorot dipadamkan, sebagian tak sanggup duduk di bangku penonton. Mereka ingin tetap bicara, ikut mengatur alur cerita, bahkan kalau perlu—menulis ulang naskahnya.
Ada ironi yang sering muncul: mereka yang dahulu lantang bicara tentang regenerasi dan keterbukaan, justru menjadi penghalang terbesar ketika harus memberi ruang bagi pengganti. Mereka tak rela jika keputusan diambil tanpa “minta izin” kepadanya. Bahkan dalam hal-hal kecil, ia ingin dilibatkan, seolah pengganti hanyalah pelaksana teknis dari pikirannya. Bukan karena mereka tidak percaya, tapi karena mereka tak siap melepaskan. Di sinilah post power syndrome menyelinap, bukan sebagai penyakit, tapi sebagai kebiasaan yang tak disadari.
Saya sering mendengar cerita dari para pemimpin muda yang menggantikan tokoh senior. Mereka bercerita bagaimana bayangan pemimpin sebelumnya terus hadir: dalam rapat, dalam kebijakan, bahkan dalam pergaulan internal. Sang mantan tak benar-benar pergi. Ia hanya bergeser posisi, tapi tetap mencengkeram. Ketika keputusan baru dibuat, selalu ada komentar, kritik, dan bisikan: "Dulu saya tidak begitu." Apa dampaknya? Inovasi terhambat, tim merasa terbelah, dan sang pemimpin baru seperti berjalan di atas garis tipis.
Ada kebutuhan manusiawi yang sangat mendasar yang sering terabaikan di sini: kebutuhan untuk merasa penting. Kekuasaan, selain memberi akses dan pengaruh, juga menjadi penanda identitas. Maka ketika jabatan hilang, rasa "siapa saya sekarang?" muncul dengan nyaring. Tak semua siap menjawabnya. Banyak yang kemudian berusaha mengganti kekosongan itu dengan menghidupkan kembali peran lamanya. Mereka jadi komentator atas keputusan-keputusan yang bukan lagi miliknya. Bahkan dalam forum sosial, mereka tetap ingin disebut dengan gelar kekuasaan yang sudah selesai.
Lucunya, fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat atas. Kepala sekolah yang pensiun pun bisa mengalami hal serupa. Ia masih merasa berhak menata ruang guru, mengatur jadwal, bahkan menegur staf baru. Semua itu dilakukan bukan karena niat buruk, tapi karena keterikatan emosional yang belum terurai. Kekuasaan telah menyatu dengan identitasnya. Dan melepaskannya sama sulitnya seperti memisahkan daun dari ranting yang telah lama kering.
Banyak orang menyangka post power syndrome hanya dialami oleh mereka yang ambisius. Tidak selalu. Justru kadang mereka yang paling tulus mengabdi, yang paling lama mengurus, yang paling mencintai pekerjaannya—adalah yang paling sulit melepas. Bagi mereka, jabatan bukan semata status, tapi rumah kedua. Maka ketika harus meninggalkannya, ada perasaan kehilangan yang dalam. Sama seperti orang tua yang harus melepas anaknya menikah—penuh restu tapi diam-diam menyimpan cemas.
Ada yang menyikapinya dengan terus hadir di lingkungan lama. Mereka datang ke kantor, duduk di ruang tamu, ikut makan siang. Kadang ikut nimbrung rapat meski tak diundang. Semuanya dilakukan dengan alasan “kangen suasana”. Tapi lama-lama, keberadaan itu menjadi beban. Bayangan masa lalu menghambat langkah masa kini. Dan pengganti pun merasa terus diawasi, bukan diberi ruang.
Saya percaya, seseorang tak perlu menduduki posisi untuk tetap memberi makna. Banyak pemimpin besar yang lebih dihormati setelah turun dari panggung, justru karena mereka tahu kapan harus mundur. Mereka menepi, bukan karena kalah, tapi karena sadar: saatnya yang lain tampil. Mereka tetap berkontribusi, tapi lewat cara yang berbeda—menulis, berbicara, memberi nasihat hanya ketika diminta.
Tantangannya adalah: tidak semua orang bisa membedakan antara kontribusi dan intervensi. Mereka yang terjebak dalam post power syndrome sering mengira campur tangan mereka adalah bentuk peduli. Mereka merasa sedang menjaga warisan, padahal sedang menghambat pertumbuhan. Mereka lupa bahwa setiap pemimpin baru punya konteks yang berbeda. Situasi berubah, tantangan berganti. Maka cara lama tak selalu relevan.
Sering kali, perasaan “saya masih tahu yang terbaik” muncul karena kesalahan dalam mengelola egonya sendiri. Ego yang dulu digunakan untuk memimpin, kini justru menjadi tembok yang menutupi kenyataan. Padahal, semakin tinggi posisi seseorang dulu, seharusnya semakin besar pula kebesaran hatinya untuk mundur. Tapi itu tidak mudah. Sebab yang ditinggalkan bukan hanya jabatan, tapi juga rasa dihormati, disambut, dan dituruti.
Budaya kita juga berperan dalam memperpanjang fenomena ini. Kita terlalu mudah menyanjung masa lalu dan enggan mengoreksi ketidaksesuaian. Kita masih suka memanggil mantan pejabat dengan gelarnya, masih memberi kursi khusus di forum-forum diskusi, dan masih meminta pendapat atas isu yang sudah tidak lagi menjadi wilayahnya. Tanpa sadar, kita ikut memelihara ilusi bahwa kekuasaan bisa diwariskan secara informal.
Tak salah menghormati mereka yang dulu berjasa. Tapi salah bila itu membuat sistem tidak berjalan sehat. Pemimpin baru perlu ruang. Ia butuh kebebasan untuk mengambil keputusan, gagal, belajar, dan tumbuh. Bila setiap langkahnya dibayang-bayangi penilaian orang lama, maka perubahan sulit terjadi. Dan organisasi hanya akan berjalan di tempat, seperti roda yang berputar tanpa bergerak.
Saya tidak sedang menyalahkan siapapun. Ini soal pemahaman. Soal kesiapan mental untuk menyambut babak baru dalam hidup. Ketika seseorang gagal menata fase pasca-kekuasaan, maka ia akan terjebak dalam nostalgia yang tidak produktif. Hidupnya diisi dengan mengomentari masa kini, bukan menjalani masa depan. Ia tak sadar, bahwa semakin ia mendikte, semakin ia kehilangan pengaruh.
Di sisi lain, tidak sedikit juga yang berhasil melewati fase ini dengan elegan. Mereka bertransformasi menjadi penasehat, mentor, atau pelaku sosial. Mereka tidak ngotot didengarkan, tapi justru semakin dihormati karena sikap bijaknya. Mereka hadir bukan untuk bersaing dengan pengganti, tapi untuk menjadi sumber refleksi. Mereka menghidupi peran barunya, tanpa mengaitkan semua pada masa kejayaannya.
Mereka tahu, kemuliaan seorang pemimpin tidak terletak pada berapa lama ia berkuasa, tetapi pada bagaimana ia mengakhiri kekuasaannya. Apakah ia mundur dengan kepala tegak dan hati lapang, ataukah ia terus menggantung di balik layar, menolak ditinggal pergi oleh zamannya? Pilihan ini menentukan apakah ia akan dikenang sebagai tokoh, atau hanya sebagai bayang-bayang yang mengganggu.
Kita perlu membangun kultur baru: bahwa setiap jabatan itu ada waktunya, dan setiap orang akan punya panggungnya sendiri. Perubahan adalah keniscayaan. Yang tidak berubah hanyalah kebutuhan untuk terus memberi makna. Maka, daripada terus berada di pinggir ring, lebih baik turun dan melatih petinju baru. Ajari mereka teknik, beri mereka semangat, lalu beri mereka ruang bertarung sendiri.
Saya percaya, bangsa yang sehat adalah bangsa yang tidak bergantung pada satu tokoh. Ia tumbuh karena ekosistemnya mendukung. Karena setiap generasi belajar dari yang lama, tapi tidak diikat olehnya. Karena pemimpin-pemimpin terdahulu legowo melepas kendali dan percaya pada estafet kepemimpinan.
Bila kita ingin sistem yang kuat, kita butuh pemimpin yang tahu kapan harus pergi. Yang tidak memaksakan cara lama untuk zaman baru. Yang tidak memonopoli kebenaran. Karena pada akhirnya, kepemimpinan bukan soal siapa yang paling lama memimpin, tapi siapa yang paling bijak mengakhiri kepemimpinannya.






.jpeg)







:quality(65):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/08/15/e9a88d37-605c-4ad8-941c-09b01ce89dbf_jpg.jpg)









:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andi-Azhar-PhD-CDMP.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andi-Azhar-OPINI204.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Kesehatan-Mental-Mahasiswa-Dan-Perguruan-Tinggi-di-Indonesia-Kampus-Bisa-Apa.jpg)

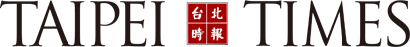



0 comments