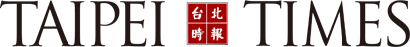Menghadiri acara kumpul keluarga besar atau reuni teman lama itu ibarat memasuki medan perang tanpa senjata, kita datang dengan niat silaturahmi tapi pulang sering kali membawa luka batin yang tak berdarah. Bayangkan saja, Anda sudah dandan maksimal, pakai baju terbaik yang sudah disetrika licin, dan menyemprotkan parfum mahal demi kesan pertama yang menggoda, eh, malah disambut dengan pertanyaan yang meruntuhkan mental. Di Indonesia, basa-basi itu memang budaya luhur, tapi entah kenapa sering kali berubah menjadi ajang interogasi terselubung yang bikin kita pengin menelan taplak meja bulat-bulat. Bukannya menanyakan kabar kesehatan atau membahas isu pemanasan global yang lebih intelektual, topik pembicaraan justru menukik tajam ke ranah privat yang sensitifnya minta ampun. Sepertinya, bagi sebagian orang, belum afdal rasanya kalau bertemu orang lain tanpa melontarkan komentar yang bikin lawan bicaranya senyum kecut sambil menahan gejolak emosi di dada. Niat hati ingin mengakrabkan diri, tapi diksi yang dipilih malah terdengar seperti hakim yang sedang membacakan vonis kesalahan terdakwa di pengadilan.
 |
| Ilustrasi (Gambar : AI Generated) |
Salah satu kalimat pembuka yang paling legendaris dan seolah menjadi standar operasional prosedur dalam perjumpaan adalah komentar soal fisik, “Wah, Mas Andi kok sekarang makin subur saja, ya?” Kalimat ini terdengar sopan karena menggunakan kata ‘subur’, padahal kita semua tahu itu cuma eufemisme halus untuk mengatakan “kamu gendut banget sekarang”. Bagi mereka yang melontarkan, mungkin itu sekadar observasi visual yang lewat begitu saja di kepala tanpa filter, semacam refleks mata langsung ke mulut. Namun, bagi si penerima yang mungkin sudah berbulan-bulan mati-matian diet karbo dan lari sore demi menurunkan satu kilogram saja, kalimat itu adalah petir di siang bolong yang menghanguskan semangat. Rasanya ingin sekali saya jawab kalau badan ini membengkak karena kebanyakan menelan omongan tetangga yang tidak bermutu, tapi tentu saja saya hanya bisa nyengir kuda.
Padahal, urusan berat badan orang lain itu sama sekali tidak merugikan beras di dapur mereka, tapi kenapa mereka yang repot mengurusi lingkar pinggang kita?
Masalahnya tidak berhenti di urusan lemak tubuh semata, karena setelah fisik, sasaran tembak berikutnya biasanya bergeser ke status reproduksi dan demografi keluarga. Bagi pasangan yang baru menikah atau sudah lama menikah tapi belum dikaruniai momongan, pertanyaan "Anakmu sudah berapa sekarang?" atau "Kok belum isi juga, nunggu apa lagi?" adalah teror mental yang lebih kejam daripada tagihan pinjol.
Orang-orang ini bertanya dengan entengnya seolah-olah bikin anak itu semudah bikin akun email baru, tinggal klik daftar dan jadi dalam hitungan detik. Mereka tidak pernah tahu perjuangan macam apa yang sedang dilalui pasangan tersebut, mulai dari program hamil yang menguras tabungan hingga doa-doa malam yang dipanjatkan sambil menangis. Sungguh sebuah ironi, orang sedang berjuang menata hati menerima takdir, malah dihakimi dengan pertanyaan yang sebetulnya tidak butuh jawaban, melainkan cuma butuh kepuasan kepo semata. Mbok ya kalau memang mau basa-basi, tanya saja "Sudah makan belum?" itu jauh lebih manusiawi dan berpotensi menyelamatkan perut yang lapar.
Kalau lolos dari pertanyaan soal anak, jangan senang dulu, karena pos pemeriksaan berikutnya adalah soal pencapaian akademis yang biasanya menghantui para mahasiswa abadi. Pertanyaan "Kapan wisuda?" atau "Skripsinya sampai bab berapa?" itu dampaknya bisa membuat seorang mahasiswa tingkat akhir mendadak mulas dan kehilangan nafsu hidup selama seminggu penuh. Mereka pikir skripsi itu cuma soal mengetik kata-kata di laptop, padahal di baliknya ada drama dosen pembimbing yang susah ditemui, revisi yang tak kunjung usai, dan data penelitian yang sering kali tidak valid. Bertanya kapan lulus kepada mahasiswa tua itu sama tidak sopannya dengan bertanya kapan mati kepada orang yang sedang sakit keras, sama-sama bikin tertekan dan tidak membantu mempercepat proses. Seharusnya, kalau memang peduli, mereka bertanya "Butuh bantuan dana buat ngeprint skripsi nggak?" atau "Mau ditraktir kopi biar ngerjainnya semangat?", itu baru namanya basa-basi yang solutif dan barokah. Tapi ya namanya juga orang Indonesia, lebih suka melempar pertanyaan yang memancing kecemasan daripada menawarkan bantuan yang meringankan beban.
Lalu, tibalah kita pada pertanyaan pamungkas yang menyasar kaum pekerja, sebuah pertanyaan yang tujuannya jelas untuk menakar seberapa sukses (atau gagal) hidup kita di mata mereka. "Sekarang kerja di mana? Jadi PNS atau swasta? Pangkatnya sudah apa?" adalah rangkaian pertanyaan investigatif yang tujuannya untuk mengukur rasa hormat yang akan mereka berikan kepada kita. Kalau jawabannya kita kerja di perusahaan bonafide atau jadi PNS dengan seragam necis, senyum mereka akan merekah lebar penuh kekaguman palsu. Tapi coba kalau kita jawab kerja freelance atau sedang merintis usaha kecil-kecilan, tatapan mereka langsung berubah menjadi tatapan iba yang merendahkan, seolah-olah kita ini pengangguran terselubung yang butuh santunan. Padahal, kebahagiaan dan kecukupan finansial itu tidak melulu harus berseragam dinas dan berangkat pagi pulang sore, tapi menjelaskan konsep ini kepada mereka susahnya minta ampun. Mereka lupa bahwa rezeki itu pintunya banyak, tidak cuma dari pintu kantor pemerintahan atau korporasi raksasa di ibu kota.
Yang paling menyebalkan dari fenomena ini adalah pelakunya bukan hanya orang-orang tua di kampung yang mungkin wawasannya terbatas pada lingkungan sekitar. Jangan salah, kebiasaan basa-basi menyakitkan ini juga marak dilakukan oleh orang-orang kota yang katanya berpendidikan tinggi dan melek literasi digital. Gelar sarjana atau master yang berderet di belakang nama ternyata tidak menjamin seseorang memiliki kecerdasan emosional untuk memilah mana pertanyaan yang pantas dan mana yang kurang ajar. Saya sering bertemu dengan orang-orang perlente di kota yang, saat reuni atau kumpul-kumpul, pertanyaannya tetap saja seputar "Mobil lo ganti baru ya?" atau "Anak lo masuk sekolah favorit yang mana?". Ternyata, kemajuan infrastruktur dan akses informasi tidak serta-merta mengubah mentalitas feodal yang suka membanding-bandingkan nasib orang lain sebagai hiburan. Ini membuktikan bahwa sekolah tinggi itu hanya mengasah otak, tapi belum tentu mampu mengasah rasa tepa selira di dalam hati.
Saya punya teori sendiri kenapa orang-orang ini begitu ringan mulut melontarkan pertanyaan yang berpotensi melukai hati lawan bicaranya. Hipotesis saya sederhana, mereka ini adalah golongan manusia yang "mainnya kurang jauh" dan bergaulnya kurang luas dalam artian yang sesungguhnya. Mereka terjebak dalam gelembung sosial mereka sendiri, di mana semua orang di sekitarnya memiliki standar hidup, pencapaian, dan kondisi fisik yang seragam dan dianggap ideal. Karena mainnya kurang jauh, mereka menganggap bahwa semua orang di dunia ini seharusnya memiliki nasib yang sama mulusnya dengan jalan tol yang mereka lalui setiap hari. Mereka gagal memahami bahwa hidup itu spektrumnya luas sekali, ada yang bahagia dengan tubuh gemuk, ada yang damai tanpa anak, dan ada yang tenang dengan pekerjaan sederhana.
Ketidakmampuan melihat perspektif lain inilah yang membuat lidah mereka begitu tumpul empati namun tajam menghakimi.
Coba bayangkan betapa damainya dunia ini jika setiap orang menyadari bahwa setiap pertanyaan basa-basi itu punya konsekuensi psikologis bagi penerimanya. Seseorang yang ditanya "Kapan nikah?" mungkin baru saja putus cinta secara tragis atau memang memilih melajang demi merawat orang tuanya yang sakit.
Ketika pertanyaan itu meluncur, luka lama yang sedang berusaha dikeringkan kembali menganga, dan si penanya dengan tanpa dosa melenggang pergi sambil mengunyah lemper. Basa-basi itu seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan dua hati, bukan malah menjadi pisau yang mengiris salah satu pihak demi kepuasan pihak lainnya. Kita perlu mendefinisikan ulang apa itu sopan santun, karena sopan bukan hanya soal mencium tangan orang yang lebih tua, tapi juga soal menjaga perasaan orang lain agar tidak tersinggung oleh ucapan kita.
Kadang saya berpikir, apakah mungkin mereka melakukan itu karena bingung mau ngomong apa saking canggungnya suasana pertemuan? Bisa jadi, karena kehabisan topik pembicaraan, otak mereka secara otomatis mengambil jalan pintas dengan menanyakan hal-hal yang sifatnya personal dan umum. Padahal, topik di dunia ini jumlahnya miliaran, mulai dari membahas resep sambal bawang yang enak, cuaca yang makin tak menentu, sampai konspirasi pendaratan manusia di bulan. Kenapa harus memilih topik yang berisiko tinggi menyakiti hati seperti "Kok jerawatan?" atau "Mukanya kusam banget sih sekarang?". Padahal kalau mau jujur, kita juga bisa balik bertanya dengan pertanyaan yang tak kalah menohok, misalnya, "Kok situ mukanya makin tua dan keriput, ya?" Tapi tentu saja kita tidak melakukannya, karena kita masih punya akal sehat dan sisa-sisa kesopanan yang melarang kita menjadi bajingan di acara keluarga.
Sebetulnya, ada satu respons yang selalu ingin saya teriakkan saat menghadapi situasi menyebalkan macam ini, tapi selalu tertahan di tenggorokan karena takut dibilang durhaka. Ingin rasanya ketika ditanya "Gajimu berapa sekarang?", saya jawab dengan lantang, "Cukup buat beli mulutmu biar diam," tapi itu jelas akan memicu perang dunia ketiga di ruang tamu. Jadi, yang bisa kita lakukan biasanya hanya menarik napas panjang, tersenyum simpul (walau hati dongkol), dan mengalihkan pembicaraan secepat kilat. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang sudah dilatih bertahun-tahun oleh jutaan orang Indonesia demi menjaga harmoni sosial yang semu. Kita mengalah bukan karena kita lemah, tapi karena kita sadar bahwa meladeni orang yang "mainnya kurang jauh" itu hanya akan membuang energi dan tidak akan mengubah pola pikir mereka.
Fenomena kepo berkedok perhatian ini sebenarnya menunjukkan betapa masyarakat kita masih gagap dalam menghargai privasi individu sebagai sebuah hak asasi. Di luar negeri, bertanya soal gaji, status pernikahan, atau berat badan dianggap tabu dan sangat tidak sopan jika bukan dalam konteks yang sangat dekat. Di sini, batas antara perhatian dan campur tangan itu tipis sekali, setipis kulit bawang yang gampang robek kalau disentuh sedikit. Orang merasa berhak tahu urusan dapur orang lain dengan dalih "kita kan saudara" atau "kita kan teman lama", padahal persaudaraan tidak memberikan lisensi untuk mengaudit hidup orang. Perhatian yang tulus itu bentuknya dukungan dan doa, bukan pertanyaan interogatif yang membuat orang merasa seperti terdakwa di kursi pesakitan.
Mungkin sudah saatnya kita memulai gerakan revolusi mental dalam hal berbasa-basi, dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan terdekat. Kalau bertemu teman lama yang terlihat lebih berisi, tahan mulutmu untuk tidak berkomentar "Gendutan ya?", ganti dengan "Wah, kelihatan segar dan bahagia ya sekarang." Kalau bertemu saudara yang belum punya anak, jangan tanya "Kapan nyusul?", tapi doakan saja dalam hati atau ajak main keponakan yang lain supaya suasananya cair. Mengubah kebiasaan memang susah, apalagi kebiasaan yang sudah mengakar turun-temurun, tapi kalau tidak dimulai sekarang, sampai kapan kita mau mewariskan budaya nyinyir ini ke anak cucu? Kita harus memutus mata rantai pertanyaan beracun ini agar generasi berikutnya bisa berkumpul dengan lebih nyaman tanpa takut dihakimi.
Sering kali, orang-orang yang gemar bertanya hal sensitif ini berlindung di balik kalimat sakti, "Ah, kamu baperan banget sih, kan cuma nanya." Ini adalah bentuk gaslighting massal yang membuat korban merasa bersalah karena tersinggung, padahal ketersinggungan itu valid. Mereka tidak mau mengakui bahwa pertanyaan merekalah yang bermasalah, malah menyalahkan respons emosional si penerima yang dianggap terlalu sensitif. Padahal, menjadi "baper" itu wajar ketika ranah privasi kita diacak-acak oleh orang yang kontribusinya dalam hidup kita nyaris nol. Kita berhak untuk merasa tidak nyaman, dan kita berhak untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan sampah yang tidak ada faedahnya itu.
Saya jadi teringat nasihat seorang kawan bijak yang bilang bahwa mulutmu adalah harimau-mu, tapi di zaman sekarang, mulutmu adalah ukuran seberapa jauh mainmu. Semakin jauh seseorang bermain, semakin luas pergaulannya, semakin banyak ragam manusia yang dia temui, biasanya mulutnya akan semakin irit dalam mengomentari hidup orang lain. Dia paham bahwa setiap orang memanggul bebannya masing-masing, membawa beban yang tidak terlihat oleh mata telanjang, jadi dia memilih untuk diam atau bicara yang baik-baik saja. Orang yang mainnya jauh tahu bahwa keberhasilan tidak tunggal, kebahagiaan tidak seragam, dan bentuk tubuh ideal itu hanyalah konstruksi sosial yang fana. Jadi, kalau ada orang yang masih sibuk mengurusi selangkangan atau dompet orang lain, bisa dipastikan radius pergaulannya cuma sebatas dari rumah ke pos ronda.
Sebagai penutup yang (semoga) menggugah nalar, marilah kita sepakati bersama bahwa hidup ini sudah cukup berat dengan segala tagihan, cicilan, dan ketidakpastian masa depan. Janganlah kita menambah beban hidup sesama manusia dengan pertanyaan-pertanyaan basa-basi yang menyakitkan dan tidak perlu. Kalau memang tidak ada topik pembicaraan yang bermutu, diam itu jauh lebih emas dan berharga daripada berbicara tapi melukai hati kawan sendiri.
Mari belajar menjadi manusia yang kehadirannya menenangkan, bukan yang kedatangannya membuat orang lain ingin segera pura-pura ke kamar mandi demi menghindari interaksi. Jadilah orang yang asyik, yang mainnya jauh, dan yang paham bahwa sebaik-baiknya basa-basi adalah yang tidak bikin sakit hati.















.jpeg)





:quality(65):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/08/15/e9a88d37-605c-4ad8-941c-09b01ce89dbf_jpg.jpg)









:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andi-Azhar-PhD-CDMP.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andi-Azhar-OPINI204.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Kesehatan-Mental-Mahasiswa-Dan-Perguruan-Tinggi-di-Indonesia-Kampus-Bisa-Apa.jpg)