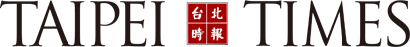Ponsel saya bergetar terus menerus sejak pagi buta, mengirimkan notifikasi dari berbagai grup WhatsApp yang isinya nyaris seragam. Ternyata ada sebuah tangkapan layar yang sedang viral dan mampir ke beranda media sosial banyak orang, membahas soal kolom pekerjaan di KTP. Isunya spesifik, tentang ada 18 jenis pekerjaan baru atau yang dipertegas, yang boleh dicantumkan secara resmi di kartu identitas kita itu. Masyarakat heboh bukan main, seolah-olah ini adalah penemuan benua baru yang mengubah tatanan hidup mereka sehari-hari secara drastis. Ada yang tertawa, ada yang mencibir, ada pula yang manggut-manggut mencoba memahami jalan pikiran birokrasi kita yang kadang memang ajaib. Sumbernya jelas, ini merujuk pada aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri terkait penatausahaan data kependudukan yang memang selalu diperbarui. Tujuannya tentu baik, untuk merapikan database penduduk agar semakin presisi dan akurat. Namun seperti biasa, respon publik selalu lebih cepat dan lebih liar daripada niat baik pembuat aturan itu sendiri.
Mata warganet, yang jeli bak elang mengincar mangsa, langsung tertuju pada satu poin yang dianggap paling nyentrik di antara daftar itu. Ada kata "Paranormal" yang kini sah dan diakui negara sebagai sebuah profesi yang bisa dicetak di atas blangko e-KTP. Sontak saja jagat maya riuh rendah dengan komentar-komentar lucu yang menggelitik perut siapa saja yang membacanya. Ada yang bertanya apakah nanti syarat melamarnya harus menyertakan sertifikat uji nyali atau surat keterangan mampu melihat makhluk halus. Ada juga yang menyindir bahwa Hogwarts cabang nusantara akhirnya mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah pusat. Padahal, kalau kita mau berpikir sedikit lebih jernih dan tenang, masuknya paranormal itu sebenarnya wajar-wajar saja dalam konteks sosiologi ekonomi.
Paranormal, atau sering kita sebut dukun dalam percakapan sehari-hari, bisa dimaknai sebagai penyedia jasa konsultasi spiritual maupun metafisika. Walaupun dari sudut pandang agama-agama samawi tertentu pekerjaan ini penuh dengan kontroversi dan perdebatan teologis, realitas sosial berkata lain. Faktanya, ada perputaran uang di sana, ada permintaan dari klien, dan ada penawaran jasa dari sang praktisi. Ini murni hukum ekonomi yang sudah berjalan ratusan tahun, bahkan mungkin sejak zaman kerajaan-kerajaan di milenium pertama. Selama ada transaksi dan ada pihak yang menghidupi dirinya dari kegiatan itu, negara wajib mencatatnya sebagai sebuah pekerjaan. Administrasi kependudukan itu buta teologi; ia hanya peduli pada data statistik dan potensi perpajakan yang mungkin bisa digali.
Namun, di tengah hiruk-pikuk orang menertawakan dukun yang kini bisa pamer KTP, perhatian saya justru tersangkut pada hal lain yang jauh lebih menggelitik nalar. Saya tidak peduli dengan paranormal, tapi saya terganggu dengan adanya pilihan "Anggota Legislatif" atau politisi sebagai sebuah jenis pekerjaan. Rasanya ada sesuatu yang mengganjal di hati, seperti ada duri dalam daging yang membuat saya sulit menelannya mentah-mentah. Kita perlu duduk sejenak, menyeruput teh hangat, dan merenungkan kembali makna filosofis dari apa yang disebut sebagai wakil rakyat itu. Apakah benar posisi terhormat itu harus dikerdilkan maknanya menjadi sekadar "pekerjaan" administratif semata?
Saya melihat ini seperti ada miskonsepsi besar yang sudah dinormalisasi oleh sistem kita tanpa kita sadari. Posisi anggota legislatif, baik di pusat maupun di daerah, sejatinya bukanlah sebuah pekerjaan dalam arti konvensional. Itu adalah jalan perjuangan, sebuah mandat suci yang diberikan oleh rakyat kepada individu yang dipercaya. Kalau posisi ini didefinisikan sebagai pekerjaan, maka logikanya akan menjadi sangat aneh dan justru berbahaya bagi demokrasi. Pekerjaan, dalam definisi paling purba sekalipun, orientasi utamanya adalah mencari nafkah atau penghasilan untuk menyambung hidup. Sedangkan menjadi anggota dewan, fokus utamanya haruslah mewakili suara masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Coba kita bayangkan apa yang terjadi di alam bawah sadar seseorang ketika ia menganggap kursi dewan itu adalah lapangan kerja. Orientasinya pasti akan bergeser, dari yang tadinya pengabdian menjadi hitung-hitungan untung rugi layaknya pedagang di pasar. Ia akan berpikir berapa modal yang sudah dikeluarkan untuk kampanye dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balik modal. Gajinya berapa, tunjangannya apa saja, dan fasilitas apa yang bisa didapatkan selama lima tahun menjabat. Ini manusiawi, karena itulah sifat dasar dari sebuah "pekerjaan" yang menuntut imbal balik materi. Akibatnya, fungsi luhur legislasi dan pengawasan akan tergeser menjadi nomor dua, kalah prioritas dibandingkan urusan dapur pribadi.
Kalau memang orientasinya adalah pekerjaan dan penghasilan, maka jangan salahkan mereka jika kinerjanya diukur dari seberapa kaya mereka setelah menjabat. Tujuan utama orang bekerja adalah mendapatkan gaji, bonus, dan pensiun yang menjamin hari tua nanti. Maka, segala daya upaya akan dikerahkan untuk memaksimalkan pendapatan itu, persis seperti karyawan mengejar target penjualan. Bedanya, kalau karyawan swasta mengejar target demi perusahaan, politisi yang merasa "bekerja" ini mengejar target demi siapa? Apakah demi rakyat, atau demi mengamankan posisi "pekerjaan" itu agar bisa diperpanjang di periode berikutnya? Logika ini membuat tupoksi legislatif menjadi kabur dan kehilangan marwahnya sebagai penyeimbang kekuasaan.
Sangat kocak rasanya, bahkan terdengar seperti lelucon satir yang pahit, kalau anggota legislatif dianggap sebagai profesi pencari nafkah. Berarti saat pemilihan umum berlangsung, masyarakat sebenarnya tidak sedang memilih wakil yang akan memperjuangkan nasib mereka. Masyarakat justru sedang menjadi departemen HRD raksasa yang sibuk melakukan wawancara kerja massal untuk ribuan pelamar. Kita semua berbondong-bondong ke TPS bukan untuk menitipkan aspirasi, melainkan untuk membantu orang lain mendapatkan pekerjaan tetap. Lha, kalau begini ceritanya, betapa baiknya hati rakyat Indonesia ini yang rela berpanas-panas demi memberi nafkah orang lain.
Dalam sebuah pekerjaan, lazimnya ada hubungan antara majikan dan buruh atau atasan dan bawahan. Kalau anggota dewan itu pekerja, lantas siapa majikan yang berhak memecatnya jika kerjanya tidak becus? Secara teori majikannya adalah rakyat, tapi dalam praktiknya rakyat tidak punya kuasa memecat di tengah jalan. Mereka hanya bisa "tidak memperpanjang kontrak" lima tahun lagi, itu pun kalau ingat dosa-dosa si pejabat. Hubungan industrial macam apa yang pekerjanya bisa tidur waktu rapat tapi gajinya tetap mengalir lancar tanpa potongan?
Lebih aneh lagi kalau kita melihat kualifikasi "pekerjaan" ini dibandingkan dengan profesi lain yang juga ada di KTP. Seorang dokter harus sekolah bertahun-tahun, koas, ujian kompetensi, baru boleh praktik menyembuhkan orang. Seorang insinyur harus paham hitungan beban supaya jembatan yang dibangunnya tidak rubuh menimpa orang lewat. Tapi untuk "pekerjaan" anggota legislatif, kadang modal utamanya hanyalah popularitas atau isi tas yang tebal. Tidak ada syarat kompetensi teknis yang ketat untuk memastikan mereka paham cara membuat undang-undang yang benar. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan seringkali mentah dan harus direvisi berkali-kali karena yang membuatnya tidak paham substansi.
Saya teringat pada semangat para pendiri bangsa ini puluhan tahun yang lalu saat merumuskan negara. Mereka tidak pernah berpikir bahwa menjadi anggota KNIP atau DPR masa itu adalah sebuah karir untuk menumpuk harta. Bagi Bung Hatta atau Sjahrir, politik adalah jalan yang sunyi, penuh penderitaan, dan seringkali berujung penjara atau pembuangan. Tidak ada dari mereka yang mencantumkan "Revolusioner" atau "Politisi" di kartu identitas mereka sebagai sarana mencari makan. Mereka punya profesi asli sebagai guru, dokter, penulis, pengacara, dan politik adalah sarana bakti mereka pada ibu pertiwi. Pergeseran makna inilah yang membuat kita sekarang merasa ada yang hilang dari kualitas negarawan kita.
Ketika negara melegitimasi posisi politis ini sebagai sebuah mata pencaharian di dokumen resmi, secara tidak langsung negara sedang mendegradasi nilai pengabdian itu sendiri. Kita seolah diajarkan bahwa berpolitik itu ya untuk cari kerja, bukan untuk menyumbangkan pikiran bagi kemajuan bangsa. Anak-anak muda kita akan tumbuh dengan cita-cita menjadi anggota dewan bukan karena ingin memperbaiki sistem, tapi karena tergiur "gaji" yang konon besar itu. Motivasi ekstrinsik berupa materi akan mengalahkan motivasi intrinsik berupa idealisme yang seharusnya menjadi bahan bakar utama. Ini adalah pendidikan politik yang keliru, yang dampaknya akan kita rasakan puluhan tahun ke depan.
Coba kita lihat dari sisi beban kerja dan tanggung jawab moral yang diemban oleh mereka. Pekerja pada umumnya bertanggung jawab pada atasan dan target perusahaan yang sifatnya mikro atau sektoral. Tapi anggota legislatif bertanggung jawab pada nasib jutaan orang, pada kualitas udara yang kita hirup, dan pada harga beras yang kita beli. Menyetarakan beban moral seberat itu dengan sekadar "pekerjaan" administratif adalah sebuah penyederhanaan yang kejam. Seharusnya, status mereka di KTP dikosongkan saja atau diberi tanda khusus sebagai "Pejabat Negara", bukan disamakan dengan buruh, pedagang, atau bahkan paranormal tadi.
Banyak orang yang tidak menyadari bahwa istilah "pekerjaan" itu membawa implikasi psikologis yang kuat pada pelakunya. Seorang pekerja akan selalu menuntut haknya terlebih dahulu sebelum menunaikan kewajibannya secara maksimal. Kita sering mendengar anggota dewan menuntut gedung baru, menuntut mobil dinas baru, atau fasilitas laptop terbaru. Itu adalah mentalitas karyawan yang merasa fasilitas kantornya kurang memadai untuk menunjang kinerjanya. Padahal, pejuang rakyat seharusnya siap bekerja di bawah pohon rindang sekalipun asalkan aspirasi rakyat bisa tersalurkan dengan baik.
Kesalahan berpikir ini juga merembet pada bagaimana partai politik melakukan rekrutmen kader-kadernya di daerah. Partai menjadi seperti agen penyalur tenaga kerja yang menjanjikan posisi basah bagi siapa saja yang mau membayar mahar. Kaderisasi tidak lagi didasarkan pada ideologi atau kemampuan berdiplomasi, melainkan pada kemampuan logistik untuk memenangkan "lowongan" tersebut. Jadilah partai politik kita terjebak dalam pragmatisme transaksional yang ujung-ujungnya merugikan rakyat banyak. Siklus ini berputar terus tanpa henti, dan kita sebagai rakyat hanya bisa menonton sambil mengelus dada.
Lalu bagaimana dengan paranormal yang tadi sempat diributkan oleh warganet di awal tulisan ini? Justru paranormal itu lebih jujur statusnya sebagai pekerja karena ada akad jual beli jasa yang jelas antara dia dan pasiennya. Kalau dukun gagal menyembuhkan, pasien bisa komplain atau setidaknya tidak akan datang lagi ke tempat praktik itu. Ada mekanisme pasar yang berjalan adil. Pelayanan buruk berarti tidak laku, pelayanan bagus berarti antrean panjang. Sementara di dunia politik, seringkali pelayanan buruk pun tetap bisa terpilih lagi karena lihai memoles citra atau menebar sembako.
Mungkin sudah saatnya kita merevisi cara pandang kita terhadap definisi profesi dalam administrasi negara kita yang kaku ini. Biarkanlah kolom pekerjaan di KTP itu diisi oleh hal-hal yang sifatnya keahlian atau profesi teknis saja. Politisi, bupati, gubernur, hingga presiden adalah jabatan politik yang sifatnya sementara (adhoc) dan berbatas waktu. Setelah masa jabatannya habis, mereka harus kembali ke pekerjaan aslinya atau menjadi pensiunan yang terhormat. Jangan biarkan jabatan itu melekat seolah-olah itu adalah identitas abadi yang memberi makan anak istri selamanya.
Kita merindukan masa di mana orang masuk ke gedung dewan dengan gemetar karena takut tidak amanah, bukan dengan senyum lebar karena membayangkan slip gaji. Kita butuh orang-orang yang "sudah selesai" dengan dirinya sendiri, yang nafkahnya sudah tercukupi dari sumber lain. Sehingga ketika mereka duduk di kursi empuk itu, yang ada di kepala mereka hanyalah bagaimana membuat rakyat sejahtera. Bukan bagaimana caranya supaya dapur tetap ngebul setelah lima tahun nanti tidak lagi menjabat.
Kondisi sekarang ini ibarat kita sedang membiarkan virus mentalitas "aji mumpung" berkembang biak secara legal dan terstruktur. Kalau terus dibiarkan, jangan kaget kalau nanti kualitas undang-undang kita makin hari makin aneh dan tidak membumi. Karena yang membuatnya bukan lagi para begawan yang bijaksana, melainkan para pencari kerja yang sedang kejar setoran. Dan kita, rakyat jelata, adalah konsumen yang dipaksa membeli produk gagal itu setiap hari.
Ah, sudahlah, mungkin saya saja yang terlalu baper menanggapi urusan administratif sekecil kolom KTP ini. Tapi bukankah dari hal-hal kecil seperti inilah karakter sebuah bangsa terbentuk dan tercermin dengan nyata? Biarlah paranormal tetap ada di sana, setidaknya mereka tidak memakan uang pajak rakyat untuk membeli kemenyan. Sedangkan mereka yang mengaku wakil rakyat itu, biayanya kita yang tanggung, tapi kerjanya entah untuk siapa.



















:quality(65):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/08/15/e9a88d37-605c-4ad8-941c-09b01ce89dbf_jpg.jpg)









:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andi-Azhar-PhD-CDMP.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andi-Azhar-OPINI204.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Kesehatan-Mental-Mahasiswa-Dan-Perguruan-Tinggi-di-Indonesia-Kampus-Bisa-Apa.jpg)