DOSEN DAN INDUSTRI INDEX JURNAL
Baca Juga
Ada satu kebiasaan baru di dunia kampus Indonesia yang kalau dipikir-pikir agak absurd tapi nyata, dosen sekarang bukan lagi sibuk ngajar atau riset di lapangan, tapi sibuk nyari jurnal. Iya, nyari jurnal. Bukan nyari ilmu, bukan nyari murid, tapi nyari tempat di mana tulisannya bisa dimuat, terutama kalau ada logo kecil bertuliskan indexed by Scopus. Logo itu sekarang sudah seperti tanda tangan Tuhan di dunia akademik. Kalau ada, maka dosen dianggap suci.
Obrolan di ruang dosen pun berubah. Dulu masih bisa santai ngomongin resep gulai, gosip mahasiswa, atau ngerumpi tentang rektor baru. Sekarang topiknya cuma satu: Scopus. Kalau tidak ngomong Scopus, ya ngomong Sinta. Dua kata yang terdengar seperti nama orang tapi bisa menentukan hidup-matinya seorang dosen. Kadang saya pikir, kalau Scopus dan Sinta itu benar-benar manusia, mungkin mereka sudah jadi tamu kehormatan setiap rapat senat universitas.
Saya pernah mendengar satu cerita. Ada seorang dosen muda, belum genap dua tahun ngajar, tapi sudah seperti pejuang yang kehilangan arah. Ia berkata lirih, “Mas, saya capek. Semua orang nyuruh saya publikasi Scopus. Saya belum sempat meneliti, tapi sudah dituntut publikasi.” Saya cuma bisa menepuk bahunya dan bilang, “Sabar, Nak. Di dunia ini, tidak semua yang terindeks Scopus itu benar-benar berguna.”
Sekarang ini, setiap dosen seperti hidup dalam sistem yang diciptakan untuk membuat mereka terus berlari, tapi tidak tahu tujuannya ke mana. Mau naik jabatan? Scopus. Mau naik pangkat? Scopus. Mau jadi guru besar? Scopus. Bahkan mau makan di kantin pun, topik obrolannya tetap Scopus. Dosen yang tidak punya publikasi Scopus itu sekarang seperti warga kelas dua. Sekalipun dia mengajar dengan hati dan mengubah hidup banyak mahasiswa, tetap saja dianggap kurang “bermutu.”
Masalahnya, Scopus ini sudah jadi industri. Bukan sekadar platform indeks. Ia sudah berubah jadi sistem ekonomi tersendiri. Ada jurnal yang menawarkan publikasi cepat, ada yang buka jalur khusus fast track, ada pula yang terang-terangan minta “biaya pemrosesan.” Dunia akademik pun pelan-pelan berubah jadi dunia perniagaan. Di kampus, pengetahuan diperdagangkan seperti gorengan di pinggir jalan. Bedanya, gorengan bisa dimakan.
Lucunya lagi, para dosen jadi seperti pekerja lepas di pabrik tulisan. Ada yang rela begadang seminggu penuh demi satu paper. Ada yang rela jual motor demi bayar biaya publikasi. Ada juga yang rajin ikut webinar internasional, bukan untuk menambah ilmu, tapi untuk numpang nama di proceeding. Semua ini dilakukan demi satu hal: index Scopus. Kalau Scopus adalah agama, mungkin para dosen ini sudah dianggap jamaah paling taat.
Saya pernah ikut satu seminar dosen muda. Di sana ada pembicara yang bilang, “Sekarang ini bukan lagi era siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling cepat publish.” Kalimat itu disambut tawa getir. Sebab semua tahu, sekarang kecepatan lebih penting daripada kedalaman. Penelitian tidak lagi tentang apa yang ditemukan, tapi di mana dimuat.
Industri ini akhirnya menciptakan lingkaran setan. Kampus menuntut dosen untuk punya publikasi internasional. Dosen pun berbondong-bondong mencari jurnal cepat terbit. Jurnal cepat terbit melihat peluang dan menaikkan tarif. Muncullah jurnal predator, yang tidak peduli isi riset, asal bayar. Dan yang lucu, kadang justru jurnal seperti inilah yang paling ramai diminati. Karena mudah, cepat, dan maaf, tidak peduli mutu.
Ada satu dosen yang saya kenal, wajahnya selalu terlihat letih tiap kali rapat. Ia bilang, “Mas, saya sampai lupa rasanya mengajar dengan tenang. Setiap kali masuk kelas, yang saya pikirkan cuma belum nulis, belum submit, belum accepted.” Dosen ini sudah lebih mirip buruh pabrik artikel. Bedanya, buruh pabrik dapat lembur. Ia tidak.
Sementara itu, mahasiswa hanya jadi penonton. Mereka melihat dosennya sibuk sendiri. Ada yang dosennya sekarang jarang datang karena lagi ngejar publikasi. Ada yang tugas akhirnya mandek karena pembimbingnya masih menunggu peer review. Dunia kampus yang dulu hidup karena interaksi kini perlahan terasa dingin. Dosen sibuk ngejar Scopus, mahasiswa sibuk ngejar dosen.
Ironisnya, sebagian besar hasil riset itu bahkan tidak pernah kembali ke masyarakat. Penelitian tentang petani yang tidak pernah dibaca petani. Kajian tentang UMKM yang tidak pernah diketahui pelaku UMKM. Paper yang ditulis dengan semangat mengubah dunia, tapi hanya berakhir di repositori kampus. Dunia akademik jadi seperti pabrik mobil yang tidak pernah mengeluarkan mobilnya ke jalan.
Kalau semua penelitian hanya berakhir pada angka-angka dan indeks, untuk apa semua ini dilakukan? Bukankah tujuan ilmu pengetahuan itu seharusnya untuk kehidupan yang lebih baik? Tapi nyatanya, sekarang kita hidup di era di mana pengetahuan hanya penting kalau bisa diindeks, bukan kalau bisa dirasakan.
Dosen yang aktif menulis di media massa sering kali dianggap “tidak ilmiah.” Dosen yang rajin terjun ke masyarakat dianggap “tidak akademis.” Padahal justru mereka yang paling banyak memberi manfaat langsung. Tapi sistem kita tidak mengukur itu. Sistem kita hanya menghitung angka sitasi, bukan dampak sosial.
Saya tidak menyalahkan Scopus sepenuhnya. Ia hanyalah alat. Masalahnya adalah cara kita memperlakukannya. Di tangan kita, Scopus berubah jadi berhala. Dihormati, ditakuti, disembah. Tapi lupa bahwa berhala, betapapun besar, tetap tidak bisa memberi makna.
Kadang saya berpikir, apa jadinya kalau Socrates atau Al-Ghazali hidup di era ini? Mungkin mereka tidak akan dianggap ilmuwan besar, karena tidak punya publikasi Scopus. Padahal ilmu mereka sudah mengubah peradaban. Mereka menulis untuk manusia, bukan untuk reviewer anonim di luar negeri yang bahkan tidak tahu mereka makan apa hari itu.
Industri ini juga menciptakan hierarki baru. Dosen yang “Scopus-nya banyak” kini dipuja seperti selebritas. Dosen yang belum punya publikasi dianggap belum matang. Padahal belum tentu. Ada banyak dosen yang mengajar dengan hati, membimbing mahasiswa sampai sukses, tapi tak pernah merasa perlu memublikasikan risetnya. Ilmunya nyata, meski tidak terindeks.
Saya pernah ditanya seorang mahasiswa, “Pak, kenapa Bapak jarang nulis Scopus?” Saya jawab santai, “Karena saya lebih suka menulis yang bisa dibaca manusia, bukan mesin.” Anak itu tertawa, mungkin tidak paham, tapi setidaknya saya lega bisa jujur. Kadang, kejujuran kecil seperti itu lebih menenangkan daripada seribu kutipan.
Masalahnya, sistem ini tidak memberi ruang bagi kejujuran semacam itu. Dosen akhirnya berpura-pura sibuk riset, padahal hanya sibuk mencari tempat publish. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Mereka hanya punya waktu untuk mengejar deadline submission.
Industri ini juga menciptakan pasar baru. Ada bimbingan nulis Scopus berbayar. Ada workshop publikasi cepat. Ada lembaga yang menjual “template sukses submit.” Semua menguangkan kegelisahan dosen. Dunia akademik berubah jadi pasar malam. Penuh lampu, ramai sua22ra, tapi intinya cuma satu, jualan.
Kadang saya heran, bagaimana ilmu yang seharusnya membebaskan, kini justru menjerat para pencarinya. Dosen jadi seperti pekerja di tambang data. Menggali angka, bukan makna. Dan yang paling sedih, banyak dari mereka tidak sadar sedang dieksploitasi oleh sistem yang mereka sendiri pertahankan.
Seorang dosen senior pernah bilang pada saya, “Dulu, kami meneliti untuk menjawab pertanyaan hidup. Sekarang, kalian meneliti untuk memenuhi target kinerja.” Saya hanya bisa tertunduk. Karena beliau benar. Ilmu kini tidak lagi lahir dari rasa ingin tahu, tapi dari rasa takut tidak naik pangkat.
Saya tidak menolak publikasi internasional. Dunia memang butuh keterbukaan. Tapi yang perlu kita ingat, ilmu pengetahuan itu seharusnya bukan soal berapa kali dikutip, tapi berapa banyak hidup yang berubah karenanya. Karena sehebat-hebatnya Scopus, ia tidak pernah tahu rasanya membantu satu desa keluar dari krisis air bersih.
Kalau boleh jujur, saya rindu masa di mana dosen dikenal bukan karena jumlah sitasinya, tapi karena muridnya yang sukses. Karena di situlah sejatinya fungsi pendidikan. Bukan soal publish or perish, tapi teach and flourish.
Mungkin, sudah saatnya kita berhenti memuja Scopus dan mulai memuliakan manusia. Karena sehebat apapun artikel yang kita tulis, kalau tidak berdampak pada siapa pun di luar ruang akademik, maka semua itu tidak lebih dari karya tanpa nyawa. Dan dunia ini, sudah cukup ramai dengan karya seperti itu.
Tags:
Pendidikan
Perguruan Tinggi












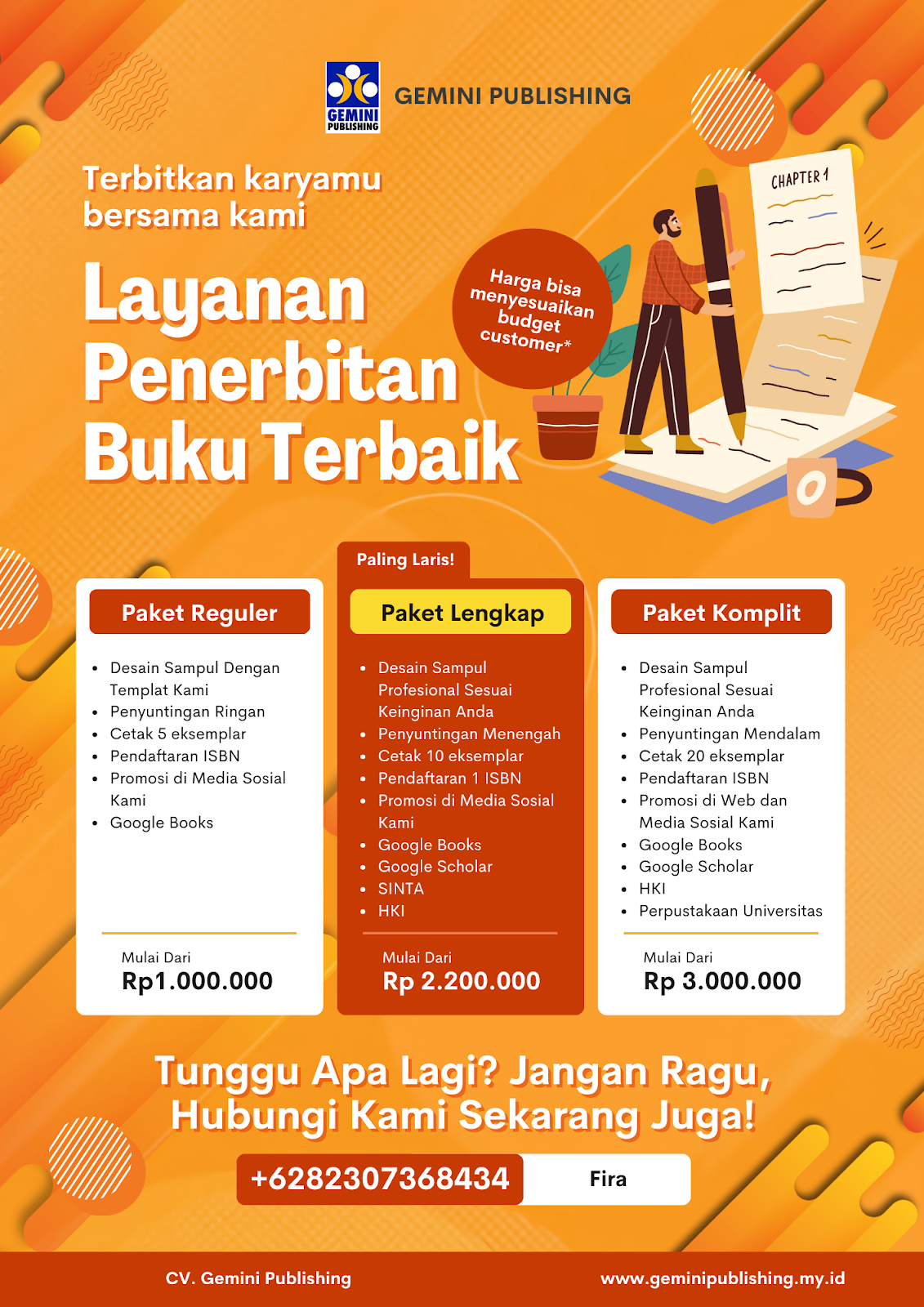

0 comments