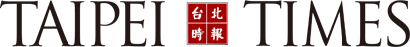Pernah suatu sore, seorang kawan sejawat datang kepada saya dengan wajah sumringah sembari memamerkan selembar kertas yang ia sebut sebagai prestasi akademik gemilang. Ia baru saja mendapatkan sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atas buku ajar yang ditulisnya setahun lalu, sebuah buku yang sejatinya sudah beredar luas di toko buku (daring dan luring) serta perpustakaan kampus. Saya mengerutkan kening, mencoba mencerna kegembiraan yang menurut saya agak salah alamat itu, sebab bukunya itu jelas-jelas sudah memiliki International Standard Book Number alias ISBN. Lha, kalau sudah punya ISBN dan terbit secara resmi, bukankah secara otomatis hak ciptanya sudah melekat pada dirinya tanpa perlu surat sakti tambahan? Kawan saya itu hanya terkekeh pelan, lantas berbisik bahwa sertifikat itulah yang ia butuhkan untuk mendongkrak poin kredit dosen yang sedang ia kejar mati-matian. Obrolan sore itu membuka mata saya pada sebuah realitas jenaka yang sedang menjangkiti dunia kampus kita belakangan ini. Rupanya, sedang terjadi gelombang pasang di mana para intelektual kampus berbondong-bondong mendaftarkan buku mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual demi selembar kertas pengakuan. Saya jadi bertanya-tanya, apakah ini bentuk ketidaktahuan kolektif atau sebuah pragmatisme yang dipaksakan oleh sistem yang mbulet?
Fenomena ini, jika diamati dari kacamata orang awam sekalipun, terasa ganjil dan menggelitik nalar sehat kita yang paling mendasar. Buku yang sudah diterbitkan oleh penerbit, apalagi anggota IKAPI, secara otomatis dilindungi oleh undang-undang hak cipta begitu karya itu mewujud dalam bentuk nyata. Tidak perlu ada pendaftaran ulang, tidak perlu ada sertifikasi tambahan, dan tidak perlu ada validasi administratif untuk membuktikan bahwa tulisan itu milik si penulis. Namun, realitas di lapangan menunjukkan antusiasme yang berbanding terbalik dengan logika hukum tersebut, seolah-olah perlindungan hukum otomatis itu dianggap tidak ada harganya. Kampus-kampus berlomba mendorong dosennya untuk "meng-HaKI-kan" segala hal, mulai dari modul, diktat, hingga buku referensi yang sudah mapan. Seakan-akan, sebuah karya belum sah sebagai kekayaan intelektual jika belum ada stempel dari Kementerian Hukum yang menyertainya. Padahal, esensi perlindungan hak cipta itu bersifat deklaratif, bukan konstitutif seperti paten atau merek dagang yang memang butuh pendaftaran. Tapi ya mau bagaimana lagi, arus deras birokrasi seringkali lebih kuat daripada bendungan logika.
Secara nalar, mendaftarkan HaKI untuk buku yang sudah ber-ISBN itu ibarat seseorang yang sudah memakai celana panjang, lalu ia memakai sarung lagi di luarnya, dan masih ditambah memakai jubah panjang. Semuanya berlapis-lapis demi menutupi sesuatu yang sebenarnya sudah tertutup dengan baik dan aman sejak lapisan pertama. ISBN itu sendiri adalah identitas unik yang melekat pada satu judul buku, yang datanya sudah terekam di Perpustakaan Nasional dan menjadi rujukan internasional. Ketika buku itu terbit, hak moral dan hak ekonomi penulis sudah terlindungi sejak detik pertama buku itu dipublikasikan ke masyarakat luas. Menambahkan sertifikat HaKI di atasnya tidak menambah proteksi hukum apa pun yang lebih kuat daripada yang sudah ada. Itu hanyalah redundansi, sebuah pengulangan yang membuang waktu, tenaga, dan biaya yang semestinya bisa dialokasikan untuk riset yang lebih bermutu. Sayangnya, nalar sederhana ini seringkali tumpul ketika berhadapan dengan tuntutan administratif yang kaku. Kita menjadi bangsa yang gemar menumpuk dokumen tapi lupa pada substansi perlindungan karya itu sendiri.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebenarnya sudah sangat gamblang menjelaskan posisi karya tulis dalam ekosistem kekayaan intelektual di republik ini. Di sana disebutkan bahwa pelindungan Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, negara sudah menjamin hak dosen atas bukunya tanpa dosen itu perlu repot-repot mengurus sertifikat surat pencatatan ciptaan. Tapi, pasal-pasal dalam undang-undang ini tampaknya kalah sakti dibandingkan dengan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen. Para dosen lebih takut pada asesor yang mengurangi nilai daripada percaya pada jaminan undang-undang negara. Ketakutan ini beralasan, karena nasib karir mereka memang lebih banyak ditentukan oleh checklist borang daripada oleh pemahaman hukum yang benar. Akibatnya, hukum berjalan di satu rel, sementara praktik administrasi kampus berjalan di rel lain yang seringkali bertabrakan. Dan di tengah tabrakan itu, dosenlah yang menjadi korbannya, terjepit di antara idealisme hukum dan realitas birokrasi.
Bayangkan betapa lucunya jika J.K. Rowling harus mendaftarkan sertifikat HaKI terpisah untuk setiap novel Harry Potter yang diterbitkannya, padahal bukunya sudah terjual jutaan kopi. Di dunia internasional, praktik mendaftarkan hak cipta (copyright) secara terpisah untuk buku yang sudah diterbitkan (published) adalah sesuatu yang sangat jarang dilakukan kecuali untuk kasus sengketa legal yang spesifik. Mekanisme "copyright page" di halaman awal buku itu sudah menjadi pernyataan hukum yang sah dan diakui di seluruh dunia beradab. Namun, di Indonesia, kita menciptakan kerumitan sendiri dengan menganggap bahwa pernyataan di halaman buku itu belum cukup "afdhal" jika belum ada sertifikat terpisah. Ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan sistemik terhadap mekanisme penerbitan buku yang sudah berlaku ratusan tahun. Kita seolah ingin menciptakan standar baru yang justru memundurkan pemahaman kita tentang properti intelektual. Alih-alih maju ke depan, kita malah sibuk berputar-putar di tempat mengurusi administrasi yang tidak perlu.
Akar masalahnya, dan ini yang paling bikin gregetan, terletak pada mentalitas birokrasi pendidikan tinggi yang terobsesi pada bukti fisik administratif ketimbang esensi karya. Dalam borang akreditasi program studi maupun dalam pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD), terdapat kolom penilaian untuk kepemilikan HaKI yang poinnya cukup menggiurkan. Poin ini seringkali menjadi penyelamat bagi dosen yang kurang dalam aspek pengajaran atau pengabdian masyarakat, sehingga sertifikat HaKI menjadi komoditas buruan. Sistem insentif ini dirancang sedemikian rupa sehingga dosen merasa "rugi" jika tidak mendaftarkan bukunya untuk mendapatkan sertifikat HaKI. Padahal, buku itu sendiri sudah dinilai dalam kategori publikasi buku, namun mereka ingin "memeras" satu karya yang sama untuk mendapatkan dua pos nilai yang berbeda. Satu buku dinilai sebagai buku referensi, dan buku yang sama dinilai lagi sebagai luaran HaKI, sebuah praktik "double counting" terselubung yang diamini oleh banyak pihak. Sistem inilah yang menyuburkan perilaku pragmatis dan membunuh nalar kritis di kalangan akademisi.
Para penilai atau asesor akreditasi pun setali tiga uang, seringkali bekerja bagaikan robot yang hanya memindai ada atau tidaknya dokumen pendukung tanpa melihat konteksnya. Mereka tidak punya waktu, atau mungkin tidak mau meluangkan waktu untuk membedah apakah sertifikat HaKI yang dilampirkan itu relevan atau sekadar duplikasi dari karya buku yang sudah dinilai di pos lain. Pokoknya, kalau ada sertifikat lambang garuda dari Kemenkumham, langsung diganjar nilai maksimal tanpa ba-bi-bu lagi. Tidak peduli bahwa isinya adalah novel pop, buku ajar kalkulus, atau kumpulan puisi galau, selama ada sertifikatnya, maka dianggap sebagai prestasi kekayaan intelektual. Sikap menggampangkan ini membuat dosen semakin bersemangat mencari jalan pintas demi memenuhi target skor yang ditetapkan. Kualitas isi buku menjadi nomor sekian, yang penting sertifikatnya bisa diunggah ke sistem SISTER atau SAPTO. Ini adalah bentuk kemalasan intelektual yang dilembagakan secara masif dan terstruktur.
Bagi sebagian besar dosen, mereka sebenarnya sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini "wagu" alias tidak pada tempatnya, namun mereka tersandera oleh tuntutan karir. Saya sering mendengar keluhan kawan-kawan dosen yang merasa terjebak dalam lingkaran setan administrasi yang tidak berkesudahan ini. Mereka tahu bahwa buku ber-ISBN itu sudah cukup, tapi aturan main di kampus mereka mewajibkan adanya luaran tambahan berupa HaKI setiap semester atau setiap tahun. Jika tidak memenuhi target, tunjangan sertifikasi dosen bisa ditahan atau bahkan pangkat akademik mereka macet tidak bisa naik. Dalam posisi terjepit seperti ini, idealisme adalah barang mewah yang sulit dipertahankan, sehingga mereka memilih jalan pragmatis: ikuti saja maunya sistem. Toh, biaya pendaftaran HaKI seringkali ditanggung oleh kampus atau bisa diambil dari dana hibah penelitian. Jadilah anggaran negara habis untuk membiayai pendaftaran sertifikat yang sebenarnya fungsinya redundan dan tidak mendesak.
Padahal jika kita mau menilik lebih dalam, HaKI itu memiliki ragam jenis dengan peruntukan yang sangat spesifik dan berbeda-beda fungsinya. Ada Paten untuk penemuan teknologi baru yang solutif, ada Desain Industri untuk bentuk estetika produk massal, ada Merek untuk identitas dagang, dan ada Hak Cipta untuk karya seni serta sastra. Mendaftarkan buku untuk mendapatkan sertifikat pencatatan ciptaan memang dimungkinkan oleh sistem, tapi bukan itu tujuan utamanya, apalagi jika buku itu sudah terpublikasi secara komersial. Fungsi pencatatan ciptaan di Dirjen KI lebih krusial untuk karya-karya yang belum terpublikasi luas atau rentan diklaim pihak lain, seperti naskah drama, kode program komputer, atau motif batik tradisional. Menggunakan mekanisme ini untuk buku ajar yang sudah jelas penerbit dan ISBN-nya adalah bentuk salah kaprah dalam memahami taksonomi kekayaan intelektual. Kita mencampuradukkan segala jenis perlindungan hukum menjadi satu keranjang besar bernama "HaKI" demi mengejar poin semata.
Karya tulis berbentuk buku, sejatinya adalah manifestasi pemikiran yang perlindungannya melekat pada eksistensi karya itu sendiri di ruang publik. Ketika seorang dosen menulis buku, ia sedang membangun reputasi akademiknya melalui penyebaran gagasan, bukan semata-mata mengamankan aset ekonomi layaknya penemu teknologi. Maka, penghargaan tertinggi bagi buku dosen adalah sitasi yang banyak, resensi yang positif, dan penggunaan buku tersebut sebagai rujukan di berbagai kampus lain. Sertifikat HaKI tidak menambah validitas ilmiah dari buku tersebut, ia hanya secarik kertas legal formal yang menyatakan "ini punya saya". Di dunia akademik yang sehat, validitas itu diuji melalui peer review dan diskursus publik, bukan melalui stempel kantor pendaftaran hak cipta. Menggeser fokus dari kualitas diskursus ke pengumpulan sertifikat adalah tanda-tanda pendangkalan intelektual yang serius.
Tengoklah bagaimana universitas-universitas kelas dunia di luar negeri memperlakukan karya buku para profesor dan penelitinya yang sangat produktif itu. Di Harvard, Oxford, atau NUS, tidak pernah terdengar adanya kewajiban bagi dosennya untuk mendaftarkan "copyright certificate" secara terpisah untuk setiap buku yang mereka terbitkan di Springer atau Routledge. Bagi mereka, kontrak penerbitan dan ISBN sudah merupakan bukti kepemilikan intelektual yang final dan mengikat secara hukum internasional. Fokus mereka adalah mendorong dosen untuk menulis buku yang groundbreaking, yang mengubah paradigma ilmu pengetahuan, bukan sibuk mengurus administrasi pendaftaran hak cipta ke kantor pemerintah. Mereka tertawa jika mendengar dosen kita sibuk mengurus sertifikat HaKI untuk buku yang sudah terbit, karena di mata mereka itu adalah pekerjaan sia-sia. Kita sibuk dengan kulit luar, sementara mereka bertarung di isi dan substansi ilmu pengetahuan.
Di sisi lain, dunia penerbitan nasional juga dibuat bingung dan geleng-geleng kepala dengan tren aneh dari kalangan akademisi ini. Penerbit merasa bahwa kontrak penerbitan yang sudah ditandatangani di atas materai adalah dokumen legal yang sah yang mengatur peralihan hak ekonomi dan perlindungan hak moral penulis. Tiba-tiba penulis datang meminta surat pengalihan hak atau dokumen pendukung lain hanya untuk mendaftarkan HaKI atas nama pribadi atau institusi. Ini seringkali memicu kerancuan hukum: siapa sebenarnya pemegang hak cipta buku tersebut jika di sertifikat HaKI tertulis nama dosen, sementara di kontrak penerbitan ada hak penerbit? Kerumitan ini menambah beban kerja administratif penerbit yang harus melayani permintaan-permintaan ajaib demi kepuasan borang akreditasi kampus. Bukannya bersinergi memajukan literasi, penerbit dan penulis malah disibukkan dengan urusan birokrasi yang tidak produktif.
Jangan lupa bahwa di balik maraknya pendaftaran HaKI ini, ada perputaran uang yang tidak sedikit yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Biaya pendaftaran Hak Cipta memang tidak semahal Paten, tapi jika dikalikan dengan ribuan dosen di seluruh Indonesia yang mengajukan setiap tahun, jumlahnya fantastis. Ini menjadi bisnis jasa tersendiri, mulai dari konsultan KI hingga PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang masuk ke kas negara. Mungkin ini salah satu alasan kenapa praktik ini dibiarkan atau bahkan didorong, karena ada aspek ekonomi yang menggiurkan bagi kas negara atau lembaga perantara. Kampus-kampus pun kini memiliki sentra HaKI yang berlomba-lomba memungut biaya layanan dari dosennya sendiri. Komersialisasi administrasi ini mengaburkan tujuan mulia dari perlindungan kekayaan intelektual itu sendiri, mengubahnya menjadi sekadar transaksi jual beli sertifikat.
Inflasi akademik sedang terjadi di depan mata kita, di mana nilai sebuah karya tidak lagi ditentukan oleh bobot ilmunya, melainkan oleh kelengkapan atribut administratifnya. Seorang dosen dengan satu buku berkualitas tinggi tapi tanpa sertifikat HaKI bisa saja kalah nilai BKD-nya dibandingkan dosen dengan buku "sampah" tapi punya sertifikat HaKI lengkap. Ini menciptakan disinsentif bagi dosen-dosen idealis yang benar-benar ingin berkarya, dan sebaliknya memberikan angin segar bagi para oportunis akademik. Akreditasi prodi pun menjadi ajang pamer jumlah sertifikat, bukan pamer dampak nyata penelitian terhadap masyarakat atau industri. Kita sedang membangun menara gading yang pondasinya terbuat dari tumpukan kertas sertifikat, rapuh dan tidak membumi. Inflasi ini berbahaya karena menciptakan ilusi prestasi semu yang membuai kita seolah-olah pendidikan tinggi kita sudah maju pesat.
Sistem kita memang gemar sekali menciptakan kerumitan yang sebenarnya bisa diurai dengan logika yang lurus dan sederhana saja. Seharusnya, kementerian terkait bisa membuat aturan tegas bahwa buku ber-ISBN tidak perlu lagi dinilai berdasarkan kepemilikan sertifikat HaKI dalam borang akreditasi. Cukup satu bukti, ISBN dan fisik buku, itu sudah mencakup poin publikasi dan perlindungan hak cipta sekaligus. Tapi, mengharapkan penyederhanaan birokrasi di negeri ini seringkali sama sulitnya dengan menegakkan benang basah. Ada ego sektoral, ada ketakutan akan hilangnya "lahan" penilaian, dan ada inersia birokrasi yang enggan berubah. Akibatnya, dosen tetap harus menari mengikuti gendang yang ditabuh oleh sistem yang irasional ini.
Budaya ini mengajarkan kepada mahasiswa kita, para calon penerus bangsa, bahwa formalitas lebih penting daripada substansi yang sesungguhnya. Mereka melihat dosen-dosennya sibuk mengurus berkas, mengejar tanda tangan, dan mengoleksi sertifikat, alih-alih berdiskusi seru tentang materi kuliah atau riset terbaru. Mahasiswa yang cerdas akan menangkap pesan tersirat, "Oh, untuk sukses di negeri ini, yang penting administrasinya beres, isinya belakangan." Ini adalah pewarisan nilai yang buruk bagi generasi masa depan yang semestinya dididik untuk menjadi inovator, bukan administrator. Kita sedang mencetak generasi birokrat, bukan generasi ilmuwan, karena contoh teladan yang mereka lihat sehari-hari adalah dosen yang disibukkan oleh borang. Pendidikan karakter yang sesungguhnya hancur lebur oleh praktik hipokrisi akademik semacam ini.
Ambil contoh konkret yang seharusnya menjadi kiblat penerapan HaKI yang benar dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa. HaKI seharusnya difokuskan pada perlindungan hasil riset hilirisasi yang bernilai ekonomi tinggi, seperti formula obat baru, alat pertanian tepat guna, atau metode pembelajaran berbasis AI. Jika seorang dosen menemukan alat pengering gabah yang hemat energi, nah, itulah yang wajib didaftarkan Paten atau Desain Industrinya agar tidak dicuri idenya oleh industri besar. Itu baru namanya melindungi kekayaan intelektual yang fungsional dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Bukan buku ajar Pengantar Manajemen yang isinya kompilasi teori umum lalu buru-buru didaftarkan hak ciptanya. Kita harus mengembalikan marwah HaKI ke tempat yang semestinya, sebagai pelindung inovasi, bukan pelindung duplikasi.
Sudah saatnya para pemangku kebijakan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk duduk bersama dengan Kementerian Hukum dan meluruskan benang kusut ini. Hentikan praktik penilaian ganda yang memicu inflasi sertifikat HaKI untuk karya buku yang sudah jelas status hukumnya. Revisi instrumen akreditasi dan panduan BKD agar lebih menghargai kualitas dan dampak (impact) dari sebuah karya, bukan sekadar menghitung lembar sertifikat. Berikan edukasi yang benar kepada para asesor agar tidak menjadi "tukang stempel" yang melanggengkan kekeliruan massal ini. Jika kebijakan di hulu tidak diperbaiki, maka sampai kiamat pun dosen-dosen kita akan terus terjebak dalam ritual administrasi yang melelahkan dan memalukan ini. Kebijakan yang waras adalah kunci untuk menghentikan kegilaan massal ini.
Perubahan harus dimulai dari kesadaran kolektif bahwa kita sedang berjalan ke arah yang salah dalam mengelola sumber daya intelektual bangsa. Dosen harus berani bersuara atau setidaknya menyadari dalam hati bahwa memburu sertifikat HaKI untuk buku ber-ISBN adalah tindakan yang menggelikan. Asosiasi dosen dan organisasi profesi semestinya menjadi garda terdepan dalam mengkritisi kebijakan borang yang tidak masuk akal ini. Kita butuh reformasi total dalam cara kita menilai kinerja akademik, sebuah reformasi yang mengembalikan dosen ke khittahnya sebagai pendidik dan peneliti, bukan pemburu sertifikat. Tanpa perubahan pola pikir, kampus kita hanya akan menjadi pabrik kertas, bukan pabrik ilmu pengetahuan.
Puncaknya, mari kita renungkan kembali apa sebenarnya tujuan kita menjadi akademisi di negara yang penuh ironi ini. Apakah kita ingin dikenal sebagai kolektor sertifikat terbanyak di rak lemari, atau sebagai penulis buku yang gagasannya dikutip dan mengubah cara pandang orang banyak? Buku adalah monumen pemikiran yang akan tetap hidup meski penulisnya sudah tiada, dengan atau tanpa sertifikat HaKI yang membingkai dinding kantor. Jangan sampai kita menjadi kaum intelektual yang, meminjam istilah lama, "pintar tapi keblinger", sibuk memagari rumah yang sebenarnya sudah aman, sementara halaman luas ilmu pengetahuan di luar sana terbengkalai tak tergarap. Sudahi mabuk sertifikat ini, mari kembali menulis buku yang bernas, berbobot, dan mencerahkan, biarkan ISBN bekerja dengan caranya sendiri.



















:quality(65):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/08/15/e9a88d37-605c-4ad8-941c-09b01ce89dbf_jpg.jpg)









:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andi-Azhar-PhD-CDMP.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andi-Azhar-OPINI204.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Kesehatan-Mental-Mahasiswa-Dan-Perguruan-Tinggi-di-Indonesia-Kampus-Bisa-Apa.jpg)