LONCENG KEMATIAN PERGURUAN TINGGI: BELAJAR DARI TAIWAN
Baca Juga
Lonceng kematian itu berdentang dari seberang lautan, namun gaungnya begitu nyaring hingga menggetarkan sendi-sendi pendidikan tinggi di tanah air. Taiwan, negeri yang selama ini kita kenal sebagai pusat inovasi teknologi dan pendidikan, kini menjadi saksi bisu dari tragedi yang tak terelakkan: penutupan sejumlah universitas terkemuka. Ming Dao, Tatung, Tung Fang, TransWorld, Chung Chou, Shoufu – nama-nama yang pernah menjadi mercusuar bagi para pencari ilmu, kini tinggal kenangan.
Penutupan ini bukanlah sekadar angka statistik atau berita sensasional belaka. Ia adalah cerminan dari krisis yang menggerogoti dunia pendidikan tinggi, krisis yang tak hanya mengancam eksistensi institusi, tetapi juga masa depan generasi muda dan daya saing bangsa. Krisis ini berakar dari perubahan demografi yang tak terelakkan, pergeseran nilai sosial, dan dinamika ekonomi yang tak kenal ampun.
 |
| Ilustrasi Perguruan Tinggi Ditutup (Gambar : Freepik) |
Di tengah gegap gempita pembangunan infrastruktur dan klaim kemajuan pendidikan, kita seolah terlena dan lupa bahwa badai demografi sedang menghampiri. Laju pertumbuhan penduduk yang melambat, bahkan mendekati nol, bukanlah sekadar angka di atas kertas. Ia adalah kenyataan pahit yang akan berdampak langsung pada jumlah calon mahasiswa, sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pembangunan.
Indonesia, dengan populasi yang jauh lebih besar, mungkin merasa aman dan terlindungi dari badai demografi ini. Namun, kita tak boleh terlena. Lonceng kematian yang berdentang di Taiwan adalah peringatan keras bagi kita semua. Ia adalah alarm bahaya yang harus membangunkan kita dari tidur panjang, mendorong kita untuk berbenah diri sebelum terlambat.
Gema Krisis Demografi dan Gelombang 'Freechild'
Krisis demografi bukanlah isapan jempol belaka, melainkan ancaman nyata yang membayangi masa depan pendidikan tinggi. Di Taiwan, badai ini telah menerjang dengan dahsyat, menyapu bersih sejumlah universitas yang tak mampu bertahan. Penurunan angka kelahiran yang drastis, diperparah dengan fenomena 'freechild', telah menciptakan jurang yang menganga antara jumlah perguruan tinggi dan calon mahasiswa.
'Freechild', sebuah istilah yang mungkin masih asing di telinga sebagian orang, merupakan fenomena sosial yang semakin menguat di berbagai negara maju. Ia merujuk pada pilihan sadar pasangan muda untuk tidak memiliki anak atau hanya memiliki satu anak. Beragam faktor melatarbelakangi pilihan ini, mulai dari tekanan ekonomi, tuntutan karier, hingga perubahan nilai sosial yang menggeser makna keluarga dan peran orang tua.
Di Indonesia, tren 'freechild' mungkin belum sekuat di negara-negara Barat. Namun, tanda-tanda awal telah terlihat. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan penurunan tingkat fertilitas total (TFR) menjadi 2,4 anak per perempuan. Angka ini memang masih di atas tingkat penggantian penduduk, namun tren penurunannya patut menjadi perhatian serius.
Teori Transisi Demografi, yang dikembangkan oleh Warren Thompson pada tahun 1929, memberikan kerangka analisis yang berguna untuk memahami fenomena ini. Menurut teori ini, setiap masyarakat akan mengalami pergeseran dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menuju tingkat kelahiran dan kematian yang rendah. Pergeseran ini terjadi seiring dengan modernisasi, urbanisasi, dan peningkatan pendidikan.
Indonesia saat ini berada pada tahap akhir dari transisi demografi, di mana tingkat kelahiran telah menurun namun tingkat kematian masih relatif tinggi. Kondisi ini menciptakan 'bonus demografi', di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dari proporsi penduduk usia non-produktif. Namun, bonus demografi ini tidak akan berlangsung selamanya. Jika tren penurunan angka kelahiran terus berlanjut, Indonesia akan memasuki era 'penuaan penduduk', di mana proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin besar. Era ini akan menjadi tantangan besar bagi pendidikan tinggi, karena jumlah calon mahasiswa akan semakin menyusut.
Bencana 'Oversupply' dan Ancaman Penutupan Kampus
Krisis demografi yang melanda Taiwan bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan penutupan sejumlah universitas terkemuka. Ada bencana lain yang mengintai, bencana yang tak kalah dahsyat: 'oversupply' perguruan tinggi. Fenomena ini, yang juga menghantui Indonesia, merupakan bom waktu yang siap meledak kapan saja.
'Oversupply' perguruan tinggi merujuk pada kondisi di mana jumlah perguruan tinggi jauh melebihi kebutuhan riil masyarakat. Di Taiwan, fenomena ini telah mencapai titik kritis. Data Kementerian Pendidikan Taiwan menunjukkan rasio perguruan tinggi terhadap penduduk yang sangat tinggi, bahkan melampaui negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang.
Indonesia pun tak luput dari jerat 'oversupply'. Liberalisasi dan desentralisasi pendidikan tinggi yang digulirkan sejak era reformasi telah membuka keran pendirian perguruan tinggi secara masif. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai lebih dari 4.500, dengan rasio perguruan tinggi terhadap penduduk yang juga tergolong tinggi.
Akibatnya, persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat. Perguruan tinggi yang tidak memiliki keunggulan kompetitif, baik dalam hal kualitas, reputasi, maupun inovasi, akan tergilas oleh seleksi alam yang kejam. Mereka akan kesulitan menarik mahasiswa, mendapatkan dana penelitian, dan mempertahankan eksistensi.
Teori Ekonomi Pendidikan, yang dikembangkan oleh Gary Becker pada tahun 1960-an, memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami fenomena ini. Menurut teori ini, pendidikan tinggi adalah investasi dalam sumber daya manusia. Individu akan memilih untuk berinvestasi dalam pendidikan tinggi jika mereka yakin bahwa investasi tersebut akan memberikan imbal hasil yang memadai, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan, status sosial, maupun pengetahuan.
Namun, dalam kondisi 'oversupply', imbal hasil dari investasi dalam pendidikan tinggi menjadi tidak pasti. Lulusan perguruan tinggi akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka, karena jumlah lulusan jauh melebihi jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya, nilai ekonomis dari gelar sarjana akan terdepresiasi.
Fenomena 'oversupply' juga berdampak negatif pada kualitas pendidikan tinggi. Perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan mahasiswa akan menurunkan standar penerimaan, mengurangi investasi dalam fasilitas dan dosen, serta mengabaikan kualitas pembelajaran. Hal ini akan menciptakan lingkaran setan yang merugikan semua pihak.
Belajar dari Taiwan, Mitigasi Risiko di Indonesia
Indonesia harus segera bertindak, belajar dari tragedi yang menimpa Taiwan. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan, menunggu badai demografi dan 'oversupply' perguruan tinggi menghantam kita tanpa ampun. Mitigasi risiko harus menjadi agenda prioritas, bukan sekadar wacana atau rencana di atas kertas.
Pertama, moratorium pendirian perguruan tinggi baru harus segera diberlakukan. Langkah ini mungkin tidak populer di kalangan pengusaha pendidikan, namun ia merupakan keniscayaan yang tak bisa ditawar lagi. Moratorium bukan berarti mematikan inovasi, melainkan memberikan ruang bagi evaluasi dan konsolidasi.
Kedua, pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap perguruan tinggi yang sudah ada. Audit ini harus dilakukan secara independen, transparan, dan akuntabel. Perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar kualitas, relevansi, dan keberlanjutan harus diberikan sanksi tegas, mulai dari pembinaan hingga penutupan.
Ketiga, diferensiasi dan spesialisasi perguruan tinggi harus menjadi strategi utama. Kita tidak bisa lagi mempertahankan model 'one size fits all' di mana semua perguruan tinggi berlomba-lomba menjadi universitas riset. Setiap perguruan tinggi harus memiliki fokus dan keunggulan masing-masing, sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.
Keempat, kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah harus diperkuat. Perguruan tinggi tidak bisa lagi menjadi menara gading yang terisolasi dari dunia nyata. Mereka harus menjadi mitra strategis bagi industri dalam mengembangkan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja.
Kelima, digitalisasi pendidikan tinggi harus menjadi prioritas. Pandemi Covid-19 telah menunjukkan bahwa pembelajaran daring bukanlah sekadar alternatif, melainkan keniscayaan. Perguruan tinggi harus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi, mengembangkan konten pembelajaran digital yang berkualitas, dan melatih dosen dalam pedagogi daring.
Keenam, internasionalisasi pendidikan tinggi harus ditingkatkan. Perguruan tinggi Indonesia harus berani bersaing di tingkat global, baik dalam hal kualitas riset, pengajaran, maupun lulusan. Kerja sama dengan perguruan tinggi asing, program pertukaran mahasiswa, dan rekrutmen dosen asing harus menjadi agenda rutin.
Ketujuh, pemerintah harus memberikan insentif bagi perguruan tinggi yang berprestasi dan berkontribusi bagi masyarakat. Insentif ini bisa berupa bantuan finansial, kemudahan akses ke sumber daya, atau pengakuan publik. Sebaliknya, perguruan tinggi yang tidak berprestasi harus diberikan sanksi, mulai dari pengurangan anggaran hingga pencabutan izin operasional.
Kedelapan, masyarakat harus diberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang perguruan tinggi. Masyarakat harus tahu perguruan tinggi mana yang berkualitas, relevan, dan berkelanjutan. Informasi ini bisa disampaikan melalui berbagai saluran, seperti media massa, situs web, dan pameran pendidikan.
Kesembilan, regulasi pendidikan tinggi harus direformasi secara menyeluruh. Regulasi yang ada saat ini terlalu kaku, birokratis, dan tidak responsif terhadap perubahan zaman. Regulasi baru harus lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Mitigasi risiko penutupan kampus bukanlah tugas mudah. Ia membutuhkan komitmen, keberanian, dan kerja sama dari semua pihak. Namun, jika kita tidak segera bertindak, kita akan menyesal di kemudian hari. Lonceng kematian yang berdentang di Taiwan adalah peringatan terakhir bagi kita. Mari kita belajar dari pengalaman mereka, mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat, dan membangun masa depan pendidikan tinggi Indonesia yang lebih baik.
***
Para pemikir pendidikan terkemuka telah lama mengingatkan kita akan bahaya yang mengintai dunia pendidikan tinggi. Mereka telah melihat tanda-tanda krisis sejak jauh hari, jauh sebelum lonceng kematian berdentang di Taiwan. Suara mereka mungkin teredam oleh hiruk-pikuk pembangunan dan klaim kemajuan, namun kata-kata mereka tetap relevan dan menggugah kesadaran.
Clark Kerr, mantan rektor Universitas California, Berkeley, dalam bukunya "The Uses of the University" (1963) telah meramalkan munculnya "multiversity", sebuah institusi yang tidak lagi memiliki identitas tunggal, melainkan terfragmentasi menjadi berbagai fakultas dan departemen yang saling bersaing. Multiversity ini, menurut Kerr, akan menjadi sarang bagi konflik kepentingan, birokrasi yang membengkak, dan penurunan kualitas pendidikan.
Bill Readings, seorang filsuf Kanada, dalam bukunya "The University in Ruins" (1996) bahkan lebih pesimistis. Ia berpendapat bahwa universitas sebagai institusi telah kehilangan makna dan tujuannya. Universitas tidak lagi menjadi tempat untuk mencari kebenaran, melainkan sekadar pabrik produksi gelar dan kredensial.
Pandangan Kerr dan Readings mungkin terdengar ekstrem, namun mereka menyentuh isu-isu fundamental yang masih relevan hingga saat ini. Krisis identitas, fragmentasi, birokrasi, dan komersialisasi pendidikan adalah masalah nyata yang dihadapi oleh banyak perguruan tinggi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Di tengah gempuran perubahan demografi dan disrupsi teknologi, perguruan tinggi harus menemukan kembali jati dirinya. Mereka harus kembali pada esensi pendidikan, yaitu mengembangkan potensi manusia secara utuh, baik intelektual, moral, maupun spiritual. Perguruan tinggi harus menjadi tempat di mana mahasiswa tidak hanya belajar untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga belajar untuk menjadi manusia yang bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan bangsa.
Kita tidak bisa lagi mengabaikan peringatan para pemikir pendidikan. Kita harus mendengarkan suara mereka, merenungkan kata-kata mereka, dan mengambil tindakan nyata untuk menyelamatkan pendidikan tinggi dari jurang kehancuran.
Membangun Masa Depan Pendidikan Tinggi yang Berkelanjutan
Penutupan universitas di Taiwan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah era baru. Era di mana pendidikan tinggi harus bertransformasi secara radikal, beradaptasi dengan perubahan zaman, atau punah ditelan gelombang disrupsi. Indonesia, dengan segala potensi dan tantangannya, memiliki peluang untuk menjadi pelopor dalam transformasi ini.
Kita tidak bisa lagi berpuas diri dengan pencapaian masa lalu. Kita harus berani keluar dari zona nyaman, mempertanyakan asumsi-asumsi lama, dan mencari solusi-solusi baru. Kita harus membangun sistem pendidikan tinggi yang tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas dan terampil, tetapi juga berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing global.
Pendidikan tinggi bukanlah sekadar pabrik produksi gelar, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Ia adalah kunci untuk membuka potensi generasi muda, menciptakan inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, investasi ini tidak akan memberikan hasil yang optimal jika kita tidak berani melakukan perubahan yang mendasar.
Kita harus berani meninggalkan model pendidikan tinggi yang ketinggalan zaman, yang hanya berfokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan teknis. Kita harus membangun model pendidikan tinggi yang holistik, yang mengintegrasikan aspek intelektual, moral, dan spiritual. Kita harus menciptakan lingkungan belajar yang merangsang kreativitas, inovasi, dan kolaborasi.
Kita harus berani menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua perguruan tinggi akan bertahan. Seleksi alam akan berjalan dengan sendirinya, menyisakan perguruan tinggi yang benar-benar berkualitas, relevan, dan berkelanjutan. Namun, seleksi alam ini tidak boleh menjadi alasan untuk pasrah dan menyerah. Sebaliknya, ia harus menjadi cambuk yang memacu kita untuk berbenah diri, meningkatkan kualitas, dan memperkuat daya saing.
Masa depan pendidikan tinggi Indonesia ada di tangan kita. Kita bisa memilih untuk menjadi penonton pasif yang hanya menyaksikan tragedi demi tragedi, atau kita bisa memilih untuk menjadi aktor aktif yang turut serta membangun masa depan yang lebih baik. Pilihan ada di tangan kita.













:quality(65):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/08/15/e9a88d37-605c-4ad8-941c-09b01ce89dbf_jpg.jpg)









:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andi-Azhar-PhD-CDMP.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andi-Azhar-OPINI204.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Kesehatan-Mental-Mahasiswa-Dan-Perguruan-Tinggi-di-Indonesia-Kampus-Bisa-Apa.jpg)

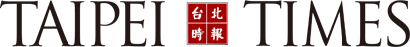



0 comments