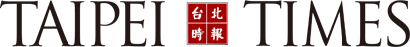Wisuda telah menjadi fenomena yang semakin umum terjadi di Indonesia, tidak hanya di jenjang perguruan tinggi, tetapi juga di tingkat pendidikan yang lebih rendah, seperti TK, SD, SMP, dan SMA. Bahkan, kelulusan penghafal kitab suci juga tidak luput dari tradisi wisuda ini. Namun, yang menjadi permasalahan bukanlah pelaksanaan wisuda itu sendiri, melainkan penggunaan toga dan atribut yang biasanya dikaitkan dengan wisuda di perguruan tinggi. Wisuda yang biasanya berkaitan dengan lulusan perguruan tinggi, di mana siswa telah menyelesaikan pendidikan tingkat lanjut, diaplikasikan pada jenjang pendidikan yang masih dalam tahap dasar. Hal ini menciptakan kesan bahwa pencapaian akademik menjadi prioritas utama dalam pendidikan, padahal tahap perkembangan anak-anak pada jenjang tersebut seharusnya lebih fokus pada pembelajaran yang holistik.
Secara umum, wisuda adalah sebuah perayaan untuk merayakan prestasi akademik dan peralihan dari satu tahap pendidikan ke tahap berikutnya. Pemakaian toga dalam wisuda memiliki makna dan simbolis yang mendalam, mewakili penyelesaian pendidikan formal dan menghormati keberhasilan akademik.
 |
| Ilustrasi (Gambar : Shutterstock/Kumparan) |
Penggunaan toga dan tradisi wisuda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan akademik di seluruh dunia. Seiring dengan berjalannya waktu, tradisi ini telah mengalami perkembangan dan mengambil berbagai makna simbolis yang mencerminkan kejayaan dan prestasi akademik.
Sejarah wisuda dapat ditelusuri kembali ke zaman Romawi kuno. Pada saat itu, wisuda merupakan suatu perayaan penting dalam proses pembelajaran. Para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan mereka akan dihormati dengan pakaian khusus sebagai tanda penghargaan atas prestasi mereka. Pada masa itu, pakaian yang digunakan bukanlah toga, tetapi robe berlengan panjang yang disebut "tunika".
Seiring dengan perkembangan zaman, wisuda dan penggunaan toga menyebar ke berbagai belahan dunia. Di Eropa, tradisi ini terus berkembang, terutama di Universitas Oxford dan Cambridge di Inggris. Pada abad ke-14, mahasiswa di kedua universitas ini mulai mengenakan toga dalam upacara wisuda mereka. Toga tersebut dipakai sebagai simbol pengetahuan dan keahlian yang mereka peroleh selama masa studi mereka.
Pada abad ke-17, tradisi wisuda dengan toga menyebar ke Amerika Serikat. Universitas-universitas seperti Harvard, Yale, dan Princeton mulai mengadopsi penggunaan toga dalam upacara wisuda mereka. Hal ini mencerminkan pengaruh kuat yang dimiliki oleh sistem pendidikan Eropa pada masa itu.
Makna dari toga dalam tradisi wisuda juga memiliki simbolis yang mendalam. Biasanya, toga memiliki warna yang berbeda-beda untuk mewakili disiplin ilmu yang ditekuni oleh para lulusan. Misalnya, toga berwarna hitam sering digunakan oleh lulusan di bidang seni dan humaniora, sementara toga berwarna biru atau hijau sering dikenakan oleh lulusan di bidang sains dan teknologi.
Selain itu, topi mortarboard yang sering dipakai dalam wisuda juga memiliki makna simbolis. Bentuknya yang kotak dan memiliki tumpal di atasnya melambangkan kejayaan akademik. Tumpal tersebut sebenarnya berasal dari simbol untuk "master" (gelar magister) yang digunakan dalam tradisi wisuda di masa lalu.
Dalam konteks global yang semakin terhubung, tradisi wisuda dan penggunaan toga menjadi ikon yang merepresentasikan prestasi dan penghormatan dalam dunia pendidikan. Meskipun ada variasi dalam tata cara pelaksanaan dan makna simbolisnya di setiap budaya, esensi dari perayaan ini tetap sama: menghargai perjalanan akademik dan merayakan keberhasilan para lulusan.
Namun, ketika tradisi wisuda dengan mengenakan toga seperti di perguruan tinggi diterapkan di tingkat pendidikan dasar dan menengah, hal itu menjadi sesuatu yang janggal dan kontroversial. Pertama, tradisi ini tidak sejalan dengan tujuan awal dari tradisi wisuda itu sendiri. Pada dasarnya, tujuan awal dari tradisi wisuda adalah untuk menghargai dan mengakui upaya serta dedikasi para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan mereka. Wisuda menjadi momen penting di mana mereka secara resmi diakui sebagai lulusan yang siap melangkah ke fase berikutnya dalam kehidupan mereka, baik itu memasuki dunia kerja, melanjutkan pendidikan tingkat lanjut ke jenjang magister, atau menjalani peran sosial yang lebih besar. Selain itu, tradisi wisuda juga bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para lulusan. Melalui upacara yang penuh simbolisme dan keindahan, mereka diingatkan akan perjuangan mereka selama bertahun-tahun dalam menyelesaikan pendidikan.
Kedua, beban finansial bagi orangtua yang tidak proporsional dengan manfaatnya. Wisuda yang semestinya berisi kebahagiaan dan kebanggaan bagi siswa dan orangtua, terkadang berubah menjadi beban finansial yang tidak proporsional dengan manfaatnya. Fenomena ini terjadi di kalangan TK hingga SMA, di mana orangtua dihadapkan pada berbagai komponen biaya yang harus dibayarkan hanya untuk sebuah seremoni yang sebenarnya bukan untuk peruntukannya. Biaya-biaya yang terkait dengan wisuda di tingkat pendidikan rendah, seperti TK atau SD, seringkali terasa berlebihan. Orangtua harus membayar biaya rias, penyewaan toga, sewa gedung, dan acara, yang kesemuanya membebani keuangan keluarga. Sebagai orangtua, mereka telah membayar biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak-anak mereka, dan tambahan biaya untuk wisuda hanya menambah beban finansial yang tidak diperlukan.
Ketiga, seremoni wisuda di tingkat pendidikan rendah cenderung kehilangan makna yang seharusnya. Tradisi wisuda seharusnya diperuntukkan bagi lulusan di perguruan tinggi, di mana mereka telah menyelesaikan pendidikan tingkat lanjut dan siap memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Namun, dengan adanya wisuda di tingkat TK, SD, atau SMA, makna awal dari tradisi ini tereduksi dan kehilangan keistimewaannya.
Keempat, secara psikologis, seremoni wisuda di tingkat pendidikan rendah dapat memberikan tekanan yang tidak perlu pada siswa. Mereka mungkin merasa terbebani dengan ekspektasi untuk tampil sempurna di hadapan orangtua dan kerabat, serta adanya tekanan untuk mengenakan pakaian dan atribut yang tidak biasa bagi mereka. Hal ini dapat menciptakan atmosfer stres dan kecemasan yang seharusnya tidak ada dalam perayaan seharusnya.
Kelima, pelaksanaan wisuda di setiap jenjang pendidikan juga dapat mengurangi nilai sakralitas tradisi wisuda itu sendiri. Wisuda seharusnya menjadi momen yang istimewa dan langka, di mana lulusan perguruan tinggi secara resmi diakui sebagai sarjana. Namun, dengan adanya wisuda di setiap tingkatan pendidikan, tradisi ini kehilangan keunikan dan kesan yang mendalam.
***
Wisuda seharusnya menjadi momen sakral yang dirayakan ketika seseorang menyelesaikan pendidikan tinggi dan memasuki dunia profesional. Jika setiap jenjang pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi melakukan wisuda, maka makna dan keistimewaan dari wisuda itu sendiri akan hilang. Ini bukan berarti kita tidak menghargai pencapaian anak-anak dan remaja dalam menyelesaikan jenjang pendidikan mereka, tetapi kita perlu merenung kembali apakah perlu mengadopsi tradisi wisuda di tingkat yang lebih rendah.
Sebagai gantinya, kita dapat mencari cara-cara lain untuk menghormati prestasi anak-anak dan remaja, seperti upacara pemberian penghargaan di sekolah atau acara lain yang lebih sesuai dengan usia dan tahap pendidikan mereka. Hal ini akan membantu memelihara makna dan nilai sakralitas wisuda di tingkat perguruan tinggi, sambil tetap memberikan apresiasi yang pantas kepada mereka yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan mereka di tingkat yang lebih rendah. Sebagai solusi yang inovatif dan lebih relevan dengan jenjang pendidikan, sekolah dapat mempertimbangkan pengenalan tradisi baru yang mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan siswa.
Pertama, penghargaan prestasi akademik dan non-akademik: Sebagai gantinya, sekolah dapat mengadakan acara penghargaan prestasi akademik dan non-akademik. Acara ini akan memberikan pengakuan kepada siswa yang telah mencapai prestasi dalam berbagai bidang, seperti akademik, seni, olahraga, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Hal ini akan mempromosikan pencapaian yang lebih holistik dan memperkuat nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam pendidikan.
Kedua, upacara penutup tahun ajaran: Sekolah dapat menggantikan tradisi wisuda dengan upacara penutup tahun ajaran yang mencerminkan perayaan kesuksesan dan kemajuan siswa selama satu tahun belajar. Acara ini dapat melibatkan pementasan seni, pengumuman penghargaan, dan momen refleksi bersama untuk menghormati perjalanan pendidikan siswa. Fokusnya bukan hanya pada kelulusan, tetapi juga pada perkembangan pribadi dan kemajuan setiap siswa.
Ketiga, proyek kemanusiaan atau lingkungan: Sebagai alternatif, sekolah dapat mengadakan kegiatan proyek kemanusiaan atau lingkungan sebagai bentuk perayaan akhir tahun. Siswa dapat terlibat dalam proyek yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau lingkungan. Misalnya, mereka dapat melakukan kegiatan penghijauan, kunjungan ke panti asuhan, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial lainnya. Hal ini akan mengajarkan nilai-nilai empati, tanggung jawab sosial, dan kolaborasi.
Keempat, acara showcase kreativitas: Sekolah dapat menyelenggarakan acara showcase kreativitas, di mana siswa dapat memamerkan hasil karya mereka dalam berbagai bidang, seperti seni, teknologi, dan penelitian. Acara ini dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengungkapkan bakat mereka, mengembangkan keterampilan kreatif, dan membangun kepercayaan diri. Hal ini juga dapat menjadi ajang inspirasi bagi siswa lainnya dan memperkuat semangat berprestasi.
Kelima, mentorship dan alumni sharing: Sebagai pengganti wisuda, sekolah dapat mengadakan sesi mentorship atau alumni sharing, di mana siswa yang akan meninggalkan jenjang pendidikan tersebut dapat mendapatkan pengarahan dan inspirasi dari para alumni. Melalui sesi ini, siswa dapat memperoleh wawasan tentang perkembangan karier dan pengalaman hidup dari para mentor atau alumni yang telah melalui masa pendidikan yang sama. Hal ini akan membantu siswa mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya dalam kehidupan mereka.
Dalam mengejar modernisasi, kita tidak boleh melupakan pentingnya menjaga kesakralan dan makna dari tradisi yang kita adopsi. Kita perlu mengenali kontroversi yang muncul dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari tindakan kita. Mari kita berpikir lebih dalam dan memilih dengan bijak untuk menjaga integritas tradisi wisuda dan memastikan bahwa setiap tahap pendidikan memiliki momen yang khas dan bermakna tanpa mengurangi nilai sakralitas wisuda di tingkat perguruan tinggi.



















:quality(65):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/08/15/e9a88d37-605c-4ad8-941c-09b01ce89dbf_jpg.jpg)









:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andi-Azhar-PhD-CDMP.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andi-Azhar-OPINI204.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Kesehatan-Mental-Mahasiswa-Dan-Perguruan-Tinggi-di-Indonesia-Kampus-Bisa-Apa.jpg)