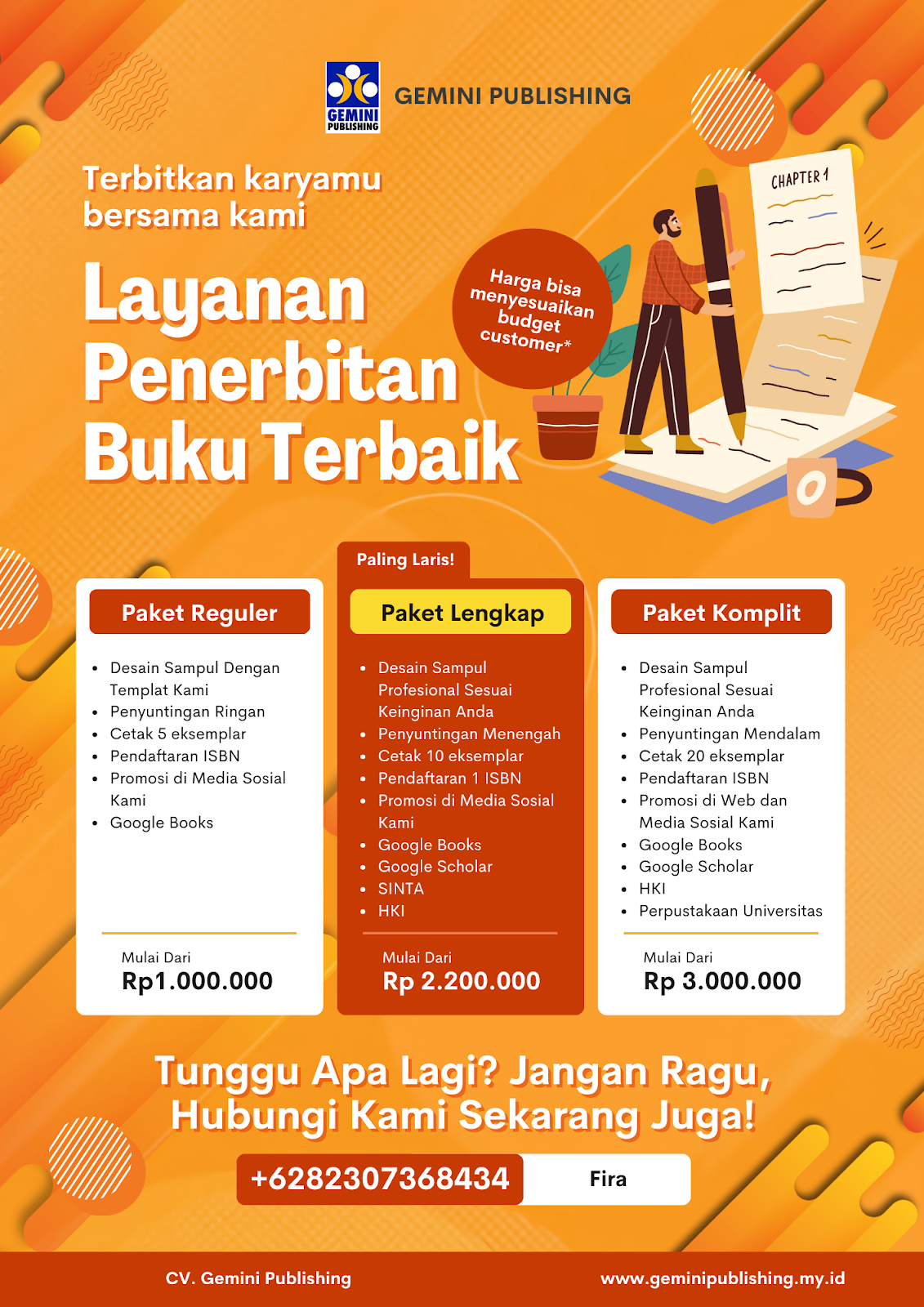Membincangkan wilayah 3T seperti Enggano sesungguhnya berbicara tentang keadilan pembangunan yang tak kunjung tiba. Pulau kecil yang menjorok ke Samudra Hindia ini kerap menjadi citra tentang tepi NKRI yang masih menanti sentuhan negara secara nyata. Selama puluhan tahun, status Enggano sebagai kecamatan di bawah kabupaten menandakan bahwa negara hadir, namun sekadar secara administratif.
Tak dapat dimungkiri, skema birokrasi yang kaku dan hierarkis justru sering memperpanjang jarak antara kebutuhan nyata warga dengan solusi kebijakan yang diharapkan. Dalam banyak kasus, keputusan strategis tentang layanan publik, infrastruktur, bahkan penanganan bencana, kerap kali harus menunggu proses panjang yang melibatkan lintas tingkatan pemerintahan. Tidak jarang, hasil akhirnya justru tak menyentuh akar persoalan.
 |
| Ilustrasi (Gambar : AI Generated) |
Bila menilik lebih dalam, model pemerintahan kecamatan di wilayah seperti Enggano ternyata lebih banyak menghadirkan batasan daripada peluang. Kewenangan yang terbatas serta anggaran yang serba pas-pasan menambah rumit upaya memajukan wilayah yang sudah sejak awal berangkat dari posisi tidak setara.
Banyak warga dan pelaku pembangunan di Enggano mengakui bahwa tantangan terbesar adalah pada kecepatan dan ketepatan respons pemerintah. Seringkali, ada jarak waktu yang sangat lama antara pengajuan kebutuhan masyarakat dengan realisasi program pemerintah. Dalam konteks ini, wilayah terluar seperti Enggano nyaris selalu menjadi prioritas kedua setelah kebutuhan daerah pusat atau kabupaten.
Ketika pembangunan berjalan lamban, masyarakat lokal harus menerima fakta bahwa akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tetap tersendat. Bahkan, dalam kondisi krisis, seperti saat pandemi atau bencana alam, respons pemerintah menjadi ujian nyata bagi tata kelola wilayah terpencil. Keadaan ini semakin menegaskan bahwa model birokrasi lama tidak sanggup menjawab kompleksitas kebutuhan wilayah 3T.
Ada pertanyaan yang mengemuka, mengapa negara belum berani mendesain ulang model pemerintahan untuk wilayah dengan tantangan unik seperti Enggano? Jawaban yang sering muncul adalah kekhawatiran akan inkonsistensi kebijakan serta potensi tumpang tindih kewenangan. Namun, jika stagnasi dibiarkan, wilayah seperti Enggano akan semakin jauh tertinggal.
Pengalaman masa lalu, di mana pemerintah pusat pernah bereksperimen dengan berbagai model pemerintahan khusus, menjadi pembelajaran penting. Model otorita Batam, otonomi khusus Papua dan Aceh, hingga keistimewaan DIY, merupakan upaya negara untuk menjawab tantangan lokalitas, meski dengan motivasi yang beragam. Namun, belum ada model yang benar-benar didedikasikan khusus bagi wilayah 3T yang berkarakter geografis dan sosial unik seperti Enggano.
Kalau kita bicara mengenai pengelolaan wilayah khusus, Batam memang sering disebut sebagai contoh otorita yang efektif. Namun, Batam adalah kawasan ekonomi strategis yang berbeda orientasinya dengan wilayah 3T. Sementara itu, Aceh dan Papua diberi otonomi khusus karena sejarah konflik dan identitas. Lalu, di mana posisi Enggano dan puluhan wilayah 3T lain yang bukan kawasan industri, bukan pula wilayah dengan status politik khusus?
Banyaknya tantangan itu memperlihatkan bahwa upaya membangun wilayah 3T harus dimulai dari desain tata kelola yang benar-benar baru dan tidak sekadar hasil adaptasi dari model lama. Justru, keberanian untuk keluar dari zona nyaman model birokrasi konvensional menjadi syarat utama agar wilayah seperti Enggano mampu mengejar ketertinggalan.
Sebagai pengajar, saya kerap mendapati bahwa logika “one size fits all” dalam tata kelola pemerintahan justru memperparah ketimpangan antarwilayah. Enggano hanyalah salah satu dari banyak wilayah yang menjadi korban generalisasi kebijakan yang tidak peka pada konteks. Sudah saatnya, negara berani mendesain sistem yang benar-benar tailor-made.
Jika menilik Undang-Undang Pemerintahan Daerah, memang ada ruang untuk pembentukan entitas administratif baru. Namun, realisasi di lapangan masih sangat minim. Salah satu sebabnya, tidak adanya model yang benar-benar relevan bagi kebutuhan wilayah 3T seperti Enggano—yang, sekali lagi, bukan wilayah industri, bukan pula kantong konflik, melainkan pulau terdepan dengan segala keterbatasannya.
Merumuskan Otorita Khusus Terintegrasi
Atas dasar refleksi panjang atas kegagalan model lama, saya menawarkan satu gagasan baru: Otorita Khusus Terintegrasi (OKT). OKT adalah model pemerintahan yang tidak sekadar menambah struktur birokrasi, namun mendesain ulang secara radikal cara negara hadir dan bekerja di wilayah-wilayah ekstrem seperti Enggano.
Dalam skema OKT, wilayah seperti Enggano dikelola oleh sebuah otorita yang bertanggung jawab langsung kepada kementerian, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Mandat yang diberikan luas dan terintegrasi, mulai dari pengelolaan layanan publik, pengembangan infrastruktur, hingga penyusunan kebijakan pembangunan. Kepala Otorita diangkat Presiden, sehingga stabilitas kepemimpinan lebih terjaga.
Dengan model ini, tidak lagi terjadi tumpang tindih atau tarik-ulur kepentingan antara kabupaten, provinsi, maupun pusat. Otorita Khusus Terintegrasi diberi kewenangan penuh dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, namun tetap dengan mekanisme pengawasan ketat dari pusat dan lembaga audit independen.
OKT juga memiliki karakteristik utama, yaitu fleksibilitas dan keterbukaan dalam merekrut tenaga profesional serta ASN dari seluruh Indonesia. Model pengelolaan sumber daya manusia ini memungkinkan wilayah 3T mendapatkan SDM terbaik dengan insentif yang kompetitif dan sistem merit yang jelas.
Lebih jauh, Otorita Khusus Terintegrasi diberikan kewenangan fiskal khusus. Anggaran yang dialokasikan tidak lagi terfragmentasi, melainkan berbentuk block grant yang dapat dikelola secara mandiri, disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas nyata di lapangan. Ini membuka ruang bagi inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Berbicara tentang regulasi, tentu pembentukan OKT membutuhkan dasar hukum yang kuat, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun revisi undang-undang terkait. Namun, urgensi pembentukan OKT dapat lebih cepat dijawab dengan mengadopsi semangat “affirmative action” untuk wilayah 3T. Dengan demikian, proses hukum berjalan seiring dengan eksekusi nyata di lapangan.
Melalui OKT, Enggano diharapkan bisa menjadi lokomotif percepatan pembangunan di wilayah 3T. Semua program dan proyek strategis bisa langsung dirancang, diputuskan, dan dieksekusi oleh Otorita, tanpa harus menunggu restu dari level pemerintahan di atasnya. Hal ini akan sangat membantu percepatan layanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar.
Model serupa sudah diterapkan di beberapa negara lain dengan karakteristik wilayah terpencil dan terluar. Misalnya, Northern Territory di Australia dan Nunavut di Kanada, yang mendapatkan kewenangan administratif langsung dari pemerintah pusat. Keberhasilan dua wilayah itu dalam menata pelayanan publik dan infrastruktur menjadi referensi penting, meski tentunya harus diadaptasi dengan konteks Indonesia.
Perlu dicatat, meski langsung di bawah kementerian, Otorita Khusus Terintegrasi tidak boleh menjadi lembaga yang tertutup. Harus ada ruang partisipasi masyarakat dan mekanisme checks and balances. Proses perumusan kebijakan, penyusunan anggaran, hingga pelaksanaan program harus terbuka bagi publik dan melibatkan pemangku kepentingan lokal.
Selain pengawasan internal dan audit eksternal, pelibatan universitas, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil akan memperkuat tata kelola OKT. Mereka berperan tidak hanya sebagai mitra pembangunan, tetapi juga sebagai watchdog yang kritis terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Pada titik ini, transformasi digital juga menjadi pilar utama. Dengan kondisi geografis Enggano yang menantang, pengelolaan layanan publik berbasis digital akan sangat membantu transparansi, efisiensi, dan kecepatan layanan. Sistem e-government bisa dioptimalkan untuk manajemen keuangan, administrasi kependudukan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan.
Tentu saja, keberhasilan Otorita Khusus Terintegrasi sangat bergantung pada komitmen politik pemerintah pusat. Alokasi dana, kejelasan kewenangan, serta konsistensi pengawasan harus benar-benar dijaga. Jangan sampai model baru ini hanya menjadi nama tanpa substansi, atau justru menjadi ruang baru bagi praktik-praktik penyimpangan.
Di sisi lain, teori administrasi negara klasik yang dikemukakan Max Weber tentang birokrasi memang menekankan pentingnya struktur hierarkis dan rasionalitas aturan. Namun, dalam konteks wilayah 3T seperti Enggano, model weberian ini acap kali justru menghadirkan hambatan baru, sebagaimana dikritik Herbert Simon lewat gagasan bounded rationality—di mana pengambilan keputusan dalam organisasi publik tidak pernah sepenuhnya rasional karena terbatasnya informasi dan sumber daya di lapangan. Dalam prakteknya, keterbatasan tersebut semakin nyata di wilayah terpencil, sehingga diperlukan lembaga yang lebih luwes dan adaptif. Menarik untuk dicermati, Elinor Ostrom pernah menegaskan bahwa kelembagaan publik harus dibangun secara tailor-made, sesuai konteks sosial dan lingkungan lokal, agar dapat benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Kemudian, konsep governance dari James Rosenau serta pendekatan collaborative governance yang diusung Ansell dan Gash mempertegas urgensi sinergi multi-aktor dalam tata kelola publik, terutama untuk wilayah-wilayah yang kompleks seperti 3T. Keduanya menyebut bahwa pemerintahan yang efektif membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat sipil dan dunia usaha, bukan hanya negara. Sementara itu, Christopher Hood dalam konsep new public management menekankan perlunya efisiensi, akuntabilitas, dan inovasi dalam organisasi publik—suatu prinsip yang sangat sesuai dengan semangat Otorita Khusus Terintegrasi yang penulis tawarkan. Dengan mengadopsi pemikiran para ahli tersebut, desain OKT bagi Enggano dan wilayah 3T lain dapat benar-benar berakar pada landasan teoritik kuat, sekaligus tetap adaptif terhadap dinamika zaman.
Menyusun Jalan Baru Wilayah 3T
Setiap kebijakan baru selalu berpotensi menimbulkan resistensi. Tidak terkecuali OKT. Penolakan bisa datang dari birokrasi lama yang merasa kehilangan kewenangan, atau dari elite lokal yang khawatir kehilangan pengaruh. Oleh sebab itu, komunikasi publik yang jujur dan dialogis sangat diperlukan sejak awal.
Masyarakat lokal perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan OKT. Mereka harus didengarkan aspirasinya, diberi ruang dalam pengawasan, dan diberdayakan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, keberadaan Otorita benar-benar menjadi milik bersama, bukan sekadar proyek dari atas.
Pemberdayaan masyarakat lokal juga menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program. Tidak cukup hanya membangun infrastruktur atau layanan publik, namun juga membangun kapasitas warga agar mampu mengelola, merawat, dan mengembangkan hasil pembangunan secara mandiri di masa depan.
Penguatan identitas dan budaya lokal menjadi bagian integral dari OKT. Setiap kebijakan pembangunan harus menghargai dan merangkul kearifan lokal, memastikan Enggano tidak kehilangan identitasnya di tengah derasnya arus modernisasi dan pembangunan.
Dalam konteks geopolitik, pembentukan Otorita Khusus Terintegrasi juga menjadi bukti nyata kehadiran negara di wilayah perbatasan. Ini sangat penting dalam mempertegas kedaulatan dan integrasi nasional, khususnya di tengah meningkatnya dinamika kawasan regional.
Tidak kalah penting, pembangunan OKT harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Setiap proyek pembangunan wajib memastikan perlindungan ekosistem pulau, mengingat Enggano adalah wilayah yang sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan. Pelibatan ahli lingkungan dan komunitas lokal mutlak diperlukan.
Di sisi lain, ekonomi lokal harus menjadi prioritas. Otorita perlu mendorong pengembangan sektor-sektor potensial, seperti perikanan, pariwisata berbasis alam, dan pertanian organik yang sesuai dengan daya dukung pulau. Dukungan teknologi tepat guna dan akses pasar juga harus menjadi agenda strategis.
Agar pelayanan publik benar-benar berkualitas, penempatan guru, tenaga kesehatan, dan ASN profesional di Enggano perlu diberikan insentif khusus dan perlakuan afirmatif. Dengan demikian, wilayah 3T tidak lagi menjadi tempat “buangan” ASN, melainkan menjadi lokasi pengabdian yang bergengsi.
Selanjutnya, sinergi dengan perguruan tinggi dan dunia usaha akan mempercepat transfer teknologi dan inovasi. Enggano bisa menjadi laboratorium inovasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kolaborasi dengan universitas akan membuka peluang riset terapan dan pengembangan kapasitas lokal yang berkelanjutan.
Dalam hal pembiayaan, Otorita perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran. Seluruh proses perencanaan dan penggunaan dana harus terbuka, dengan sistem pelaporan daring yang dapat diakses publik dan diaudit oleh lembaga independen. Ini menjadi pondasi utama membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah praktik korupsi.
Tak kalah penting adalah membangun indikator keberhasilan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup warga. Indeks kebahagiaan, kesehatan, pendidikan, dan pelestarian lingkungan menjadi ukuran utama keberhasilan OKT di masa depan.
Setiap proses perubahan membutuhkan waktu dan adaptasi. Oleh karena itu, pembentukan OKT harus diiringi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang rutin. Setiap kebijakan yang tidak berjalan efektif harus segera dievaluasi dan diperbaiki, dengan melibatkan masukan dari masyarakat dan para ahli.
Akhirnya, yang terpenting dari semua ini adalah memastikan bahwa Otorita Khusus Terintegrasi bukan sekadar solusi teknokratis, tetapi benar-benar menjadi jalan baru bagi keadilan pembangunan di wilayah 3T. Enggano harus menjadi contoh nyata bagaimana negara hadir, bukan sekadar di atas kertas, tetapi juga dalam realitas keseharian warga.
Pembentukan OKT tidak boleh dianggap sebagai proyek sementara. Ini harus menjadi komitmen jangka panjang negara dalam menuntaskan ketimpangan pembangunan. Setiap perubahan yang terjadi harus berpihak pada masyarakat, bukan pada elit atau kelompok tertentu.
Dengan kehadiran OKT, diharapkan wilayah 3T seperti Enggano tak lagi terpinggirkan. Sebaliknya, mereka justru bisa tumbuh menjadi pusat-pusat inovasi yang menginspirasi wilayah lain. Negara tidak lagi hadir sebagai “tamu”, melainkan benar-benar menjadi “tuan rumah” di rumahnya sendiri.
Afirmasi Komitmen dan Argumen Kunci
Pada akhirnya, gagasan pembentukan Otorita Khusus Terintegrasi adalah refleksi dari tanggung jawab negara yang sesungguhnya. Inilah saatnya membuktikan bahwa keadilan pembangunan tidak berhenti di pulau-pulau besar, melainkan menjangkau hingga ke pulau terluar seperti Enggano.
Argumen utama yang harus dipegang adalah tidak ada satupun wilayah yang boleh dibiarkan berjalan sendiri tanpa uluran tangan negara. OKT menjadi instrumen nyata mewujudkan janji keadilan sosial dalam konstitusi dan cita-cita Nawacita yang digadang-gadang selama ini.
Kita belajar dari kegagalan masa lalu bahwa tata kelola birokrasi lama tidak sanggup melayani kebutuhan unik wilayah 3T. Kini, keberanian dan inovasi kebijakan adalah jawaban. Dengan OKT, negara bisa melompat lebih cepat, tanpa dibelenggu pola lama yang justru menghambat.
Dengan modal desain kelembagaan yang adaptif, komitmen politik yang kuat, dan pengawasan publik yang ketat, OKT sangat mungkin menjadi lokomotif baru pembangunan di wilayah 3T. Tentu, kesuksesannya membutuhkan gotong royong semua pihak—masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.
Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Justru, menunda berarti memperdalam jurang ketimpangan dan menambah beban masa depan bangsa. Enggano dan puluhan wilayah 3T lainnya pantas memperoleh keadilan yang telah lama mereka nanti-nantikan.
Referensi dalam tulisan ini cukup sebagai penguat argumen utama, bukan sebagai ornamen akademik. Pengalaman Batam, praktik otonomi di negara lain, serta pengalaman Indonesia dalam membangun kawasan khusus menjadi bahan pembelajaran yang memperkaya argumentasi.
Saya percaya, kehadiran Otorita Khusus Terintegrasi akan menjadi babak baru dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Model ini bukan sekadar solusi teknis, tetapi sekaligus bukti kehadiran negara yang lebih adil, responsif, dan berpihak pada yang paling membutuhkan.
Semoga Enggano, dan wilayah 3T lain, segera merasakan perubahan nyata dari keberanian negara dalam mendesain ulang tata kelola wilayahnya. Hanya dengan cara inilah, Indonesia benar-benar hadir dan berdaulat di setiap jengkal tanah airnya.