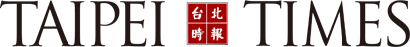Beberapa hari terakhir jagat media sosial dan ruang-ruang redaksi diramaikan oleh berita yang tak hanya menggelitik nalar publik, tetapi juga membuat banyak profesional mengernyitkan dahi. Beberapa nama yang sebelumnya duduk sebagai menteri dan wakil menteri, kini dilantik menjadi komisaris di sejumlah BUMN besar. Salah satunya bahkan diketahui tidak menamatkan pendidikan S1-nya, namun ditunjuk menjadi komisaris di perusahaan plat merah yang berperan strategis dalam perekonomian nasional. Lebih menarik lagi, latar belakangnya adalah seorang musisi band, bukan pebisnis, bukan ekonom, apalagi orang dengan pengalaman manajerial. Paling tinggi pengalaman manajerialnya adalah pimpinan partai kelas medioker.
Ini bukan sekadar guyonan dunia maya. Ini soal serius. Sebab ketika jabatan komisaris dijadikan tempat menampung tim sukses, loyalis, bahkan artis, maka arah tata kelola perusahaan negara berada di jalur yang salah. Kita semua tahu, komisaris bukan jabatan simbolik. Mereka adalah penjaga gawang, pengawas strategis yang menentukan apakah perusahaan berjalan sesuai arah atau justru tergelincir karena keputusan yang asal-asalan.
Saya tidak sedang mempermasalahkan latar belakang profesi seseorang. Banyak seniman dan musisi yang cerdas dan memiliki wawasan luas. Tapi menjadi komisaris BUMN itu bukan soal pintar bernyanyi atau punya banyak followers. Ini soal kemampuan memahami strategi bisnis, risiko pasar, dinamika ekonomi global, hingga tata kelola korporat yang sehat. Kalau hanya sekadar populer atau dekat dengan kekuasaan, lantas siapa yang akan menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan?
Bayangkan jika kita memilih pilot pesawat bukan karena kemampuannya menerbangkan pesawat, tapi karena dia sering ikut kampanye dan loyal pada partai tertentu. Apa kita rela hidup kita dipertaruhkan di tangan orang yang salah? Logika yang sama harusnya berlaku dalam dunia bisnis, terlebih ketika yang dipertaruhkan adalah uang rakyat.
BUMN bukan milik pemerintah. Mereka milik negara. Ada perbedaan besar antara “pemerintah” dan “negara”. Pemerintah bisa berganti tiap lima tahun, tapi negara adalah entitas yang harus dijaga lintas generasi. Maka, pejabat yang duduk di struktur BUMN seharusnya dipilih bukan karena kedekatannya dengan kekuasaan, tetapi karena kemampuannya menjaga aset publik ini agar terus tumbuh, kompetitif, dan memberi manfaat luas.
Satu hal yang sering dilupakan: jabatan komisaris bukan “hadiah” politik. Ia adalah posisi strategis yang menentukan hidup matinya sebuah perusahaan. Komisaris harus mampu membaca laporan keuangan, memahami portofolio bisnis, mengawasi proyek-proyek strategis, dan memastikan perusahaan taat pada prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance). Jika tidak, maka yang terjadi bukan BUMN yang maju, melainkan BUMN yang dikerjai.
Saya khawatir, dalam praktik seperti ini, yang terjadi bukan meritokrasi tapi mediokritas. Orang-orang yang seharusnya duduk karena kompetensi, tersingkir karena tidak punya kedekatan dengan elite politik. Akibatnya, talenta-talenta terbaik bangsa memilih berkarier di luar negeri atau di sektor swasta. Padahal, kita membutuhkan mereka untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dari dalam.
Sebagian orang mungkin berkata, “Ah, komisaris kan hanya duduk manis, datang rapat sesekali.” Justru itu masalahnya. Karena persepsi bahwa komisaris hanya posisi “titipan”, maka pengawasan menjadi lemah. Banyak kasus korupsi di BUMN terjadi karena pengawasan yang tidak efektif. Dan itu terjadi karena komisarisnya tidak berfungsi sebagai pengawas strategis, melainkan sekadar pelengkap struktur.
Di mata publik, BUMN adalah etalase negara. Ketika masyarakat melihat orang yang tak relevan secara keahlian menduduki posisi strategis di sana, maka kepercayaan publik ikut runtuh. Dan saat kepercayaan runtuh, maka apapun yang dilakukan BUMN akan dipandang dengan sinis, bahkan kalau itu sebenarnya adalah langkah baik.
Saya selalu percaya bahwa organisasi yang baik dibangun di atas fondasi profesionalisme. Kita bisa menengok ke belakang, ke era ketika Bank Mandiri, BNI, hingga BRI mulai bertransformasi bukan karena orang-orangnya dekat dengan penguasa, tetapi karena mereka membawa keahlian, rekam jejak, dan visi jangka panjang.
Kita bisa ambil pelajaran dari perusahaan-perusahaan global yang kuat bukan karena afiliasi politik, tapi karena struktur kepemimpinannya berisi para profesional terbaik. Apakah Apple, Toyota, atau Siemens menunjuk komisaris hanya karena mereka populer di TikTok atau aktif di partai politik? Tidak. Mereka tahu bahwa profesionalisme bukan pilihan, tapi keharusan.
Namun saya juga tidak naif. Politik adalah realitas. Saya paham bahwa dalam sistem demokrasi, selalu ada semacam “utang politik” yang ingin dibayar pasca kemenangan. Tapi membayar utang politik tidak harus merusak sistem yang sudah dibangun dengan susah payah. Ada banyak posisi yang lebih cocok untuk itu—di luar urusan bisnis negara.
Yang perlu kita tanyakan hari ini: mau kita bawa ke mana BUMN kita? Apakah kita ingin mereka menjadi pemain global, menciptakan inovasi, menguasai teknologi, membuka lapangan kerja luas? Atau kita biarkan mereka menjadi ladang balas jasa dan tempat parkir politik?
Masalahnya bukan hanya pada siapa yang duduk, tapi pada budaya dan sistem yang mengizinkan itu terjadi. Kita butuh sistem rekrutmen yang transparan, berbasis kompetensi, dan diawasi publik. Penunjukan komisaris seharusnya melewati proses seleksi terbuka, dengan uji kelayakan, bukan hanya sekedar rapat terbatas di ruangan elit.
Mari kita belajar dari masa lalu. Dulu, banyak BUMN jadi sarang korupsi dan kerugian. Salah satu penyebabnya adalah karena jabatan strategis diisi oleh orang yang tidak kapabel. Mereka tidak paham bisnis, tidak paham risiko, tapi ikut menandatangani keputusan strategis. Hasilnya: kerugian triliunan, dan akhirnya negara juga yang menalangi.
Anak muda hari ini makin kritis. Mereka tahu siapa yang layak duduk di posisi strategis dan siapa yang hanya “nebeng kekuasaan.” Kalau negara tidak segera memperbaiki pola rekrutmen ini, jangan salahkan generasi muda kalau mereka makin apatis terhadap politik dan pemerintahan.
Saya tahu, tulisan ini mungkin tidak populer bagi sebagian kalangan. Tapi ini harus dikatakan. Karena mencintai bangsa bukan berarti membiarkan kesalahan terus berulang. Justru karena cinta, kita harus berani bicara. Kalau bukan kita, siapa lagi?
Pekerjaan rumah kita bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur etika dan profesionalisme. Tanpa itu, maka gedung-gedung tinggi dan proyek-proyek megah tidak akan berarti. Kita butuh pemimpin dan pengawas yang bisa dipercaya, bukan sekadar terkenal.
Satu pertanyaan penting untuk para pengambil kebijakan: apakah kalian ingin tercatat dalam sejarah sebagai pembangun fondasi, atau sebagai perusak sistem? Sejarah akan mencatat. Dan rakyat, perlahan tapi pasti, mulai menyadari siapa yang benar-benar bekerja, dan siapa yang hanya numpang nama.
Saya percaya, kita masih punya harapan. Tapi harapan itu hanya akan hidup jika kita punya keberanian untuk memperbaiki yang salah. Dan perbaikan itu dimulai dari siapa yang kita percayakan untuk mengelola aset publik. Bukan karena dia tim sukses, tapi karena dia ahli dan layak.
Mari berhenti menjadikan komisaris sebagai jabatan pelengkap. Jadikan mereka mitra strategis yang memperkuat bisnis, bukan sekadar stempel kekuasaan. Kalau tidak, kita akan terus berada di lingkaran setan kegagalan.
Karena pada akhirnya, bukan hanya BUMN yang gagal. Tapi kepercayaan rakyat yang hilang. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar laporan keuangan merah.





















:quality(65):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/08/15/e9a88d37-605c-4ad8-941c-09b01ce89dbf_jpg.jpg)









:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andi-Azhar-PhD-CDMP.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Andi-Azhar-OPINI204.jpg)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bengkulu/foto/bank/originals/Kesehatan-Mental-Mahasiswa-Dan-Perguruan-Tinggi-di-Indonesia-Kampus-Bisa-Apa.jpg)