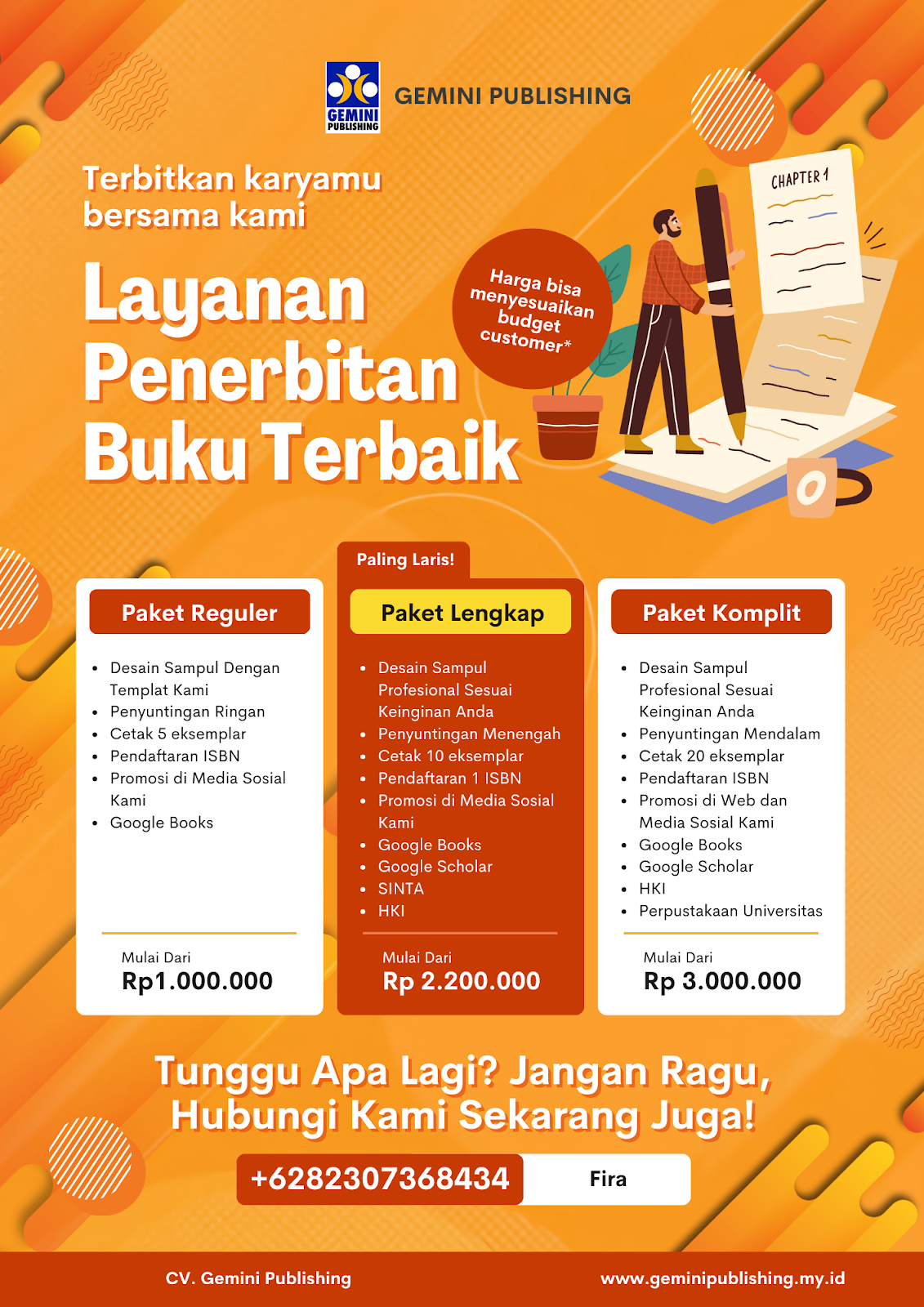Dulu, nenekku punya kebiasaan menaruh cermin kecil di ambang jendela depan rumah. Katanya, supaya sinar pagi memantul dan memberi isyarat pada pak pos bahwa rumah ini ada yang menunggu surat. Aku kecil tak mengerti maksudnya, tapi kini aku paham: menunggu surat itu bukan sekadar menanti kabar, melainkan berharap pada semesta agar seseorang di tempat jauh masih mengingatmu.
Di kampung kami, suara klakson motor pak pos adalah simfoni paling ditunggu. Anak-anak akan berhenti bermain, ibu-ibu menghentikan tumbukan bumbu di dapur, dan kakek-kakek menoleh dari kursi malas mereka. Semua berharap sepucuk kabar datang untuk mereka. Anehnya, walau tahu surat itu bukan untukku, hatiku selalu ikut deg-degan.
Surat pernah menjadi alasan seseorang bangun pagi, mandi lebih awal, dan duduk manis di depan rumah, hanya untuk melihat adakah sepucuk amplop berwarna cokelat di tangan pak pos. Kadang kosong, kadang penuh. Tapi yang selalu hadir adalah harapan, setia menempel di hati seperti perangko.
Aku masih ingat surat pertama yang kuterima: dari saudara yang bekerja di kota. Tulisannya agak miring, tintanya sedikit pudar, tapi setiap hurufnya seperti bisikan di telingaku. "belajar yang rajin ya" katanya. Aku membacanya seperti doa, dan menyimpannya dalam kotak kayu kecil yang kini sudah usang.
Kini zaman berubah. Tak ada lagi cermin kecil di jendela, tak ada lagi bel sepeda. Kotak surat di pagar sudah penuh dengan selebaran iklan. Tapi jantungku tetap bisa berdebar untuk sebuah pesan, meskipun ia datang lewat notifikasi di layar ponsel. Meski bentuknya digital, rindu yang mengantarnya tetap sama nyatanya.
Kadang aku berpikir, apa rindu bisa merambat melalui kabel serat optik? Atau apakah cinta bisa bertahan dalam format PDF? Tapi kenyataannya, satu email dari seseorang yang lama tak menyapamu, bisa membuatmu tersenyum sepanjang hari. Sungguh, esensi surat tak berubah, hanya medianya saja yang berganti rupa.
Aku punya satu folder di inbox yang kuberi nama “Surat Emas.” Di sana, kusimpan semua pesan yang membuat hatiku hangat. Ada dari guru lamaku, dari teman sepenulisan, dan dari orang-orang yang pernah berjumpa walau sesaat. Mereka bukan lagi deretan huruf biasa. Mereka adalah pelita kecil di hari yang kelabu.
Tapi tidak semua surat membawa kabar baik. Ada surat yang menjadi palu godam, menghantam dadamu tanpa aba-aba. Surat penolakan beasiswa, surat pengunduran diri dari seseorang yang kau anggap rekan abadi, atau email singkat yang berkata, “Maaf, kami memilih kandidat lain.” Sakitnya terasa, walau tak ada perangko yang menempelkannya.
Minggu lalu, aku menunggu email penting. Sebuah peluang yang kutunggu bertahun-tahun. Mereka janji akan kirim kabar hari Senin. Aku bangun lebih pagi, menyeduh kopi, duduk di depan layar. Tapi kotak masukku diam. Seperti hutan kosong setelah badai.
Hari berlalu. Selasa datang tanpa suara. Rabu pun demikian. Aku mulai membuka spam folder, siapa tahu surat itu nyasar. Tapi yang kutemukan hanyalah penawaran aneh: pelangsing herbal, pinjaman cepat, dan warisan dari pangeran Afrika yang tidak kukenal. Dunia benar-benar telah berubah.
Di tengah semua kecanggihan ini, kita jadi mudah tersesat dalam kerumitan harapan. Dulu, ketika surat datang terlambat, kita bisa menyalahkan hujan, banjir, atau jalan rusak. Tapi kini? Kita menyalahkan sistem, menyalahkan algoritma. Atau lebih sering: menyalahkan diri sendiri.
Pernah suatu malam, aku bermimpi menerima surat dengan amplop biru. Ketika kubuka, isinya hanya satu kalimat: “Maaf, kami tidak bisa menerimamu.” Anehnya, aku terbangun bukan karena sedih, tapi karena merasa lega. Seolah ketidakpastian lebih menyiksa daripada penolakan itu sendiri.
Aku mencoba menghibur diri. Mungkin surat itu sedang dalam perjalanan panjang, menyeberangi samudra data, tersesat di antara server. Atau mungkin petugas pengirimnya sedang kelelahan, dan aku hanya perlu sedikit lebih sabar. Tapi waktu adalah ular yang licin. Ia tak pernah bisa kita genggam.
Ibu pernah bilang, “Kadang, surat yang tak kunjung datang adalah cara semesta menyelamatkan kita dari kabar yang tidak siap kita terima.” Aku mengangguk saja waktu itu. Tapi kini, kalimat itu terngiang kembali, saat aku duduk memandangi kotak masuk yang hening seperti malam tanpa jangkrik.
Dalam penantian ini, aku belajar banyak tentang diriku sendiri. Bahwa aku adalah manusia yang mudah berharap. Bahwa hatiku lembut, terlalu percaya pada janji-janji. Dan bahwa aku, seperti nenekku dulu, masih ingin menaruh cermin di jendela—meskipun tak ada pak pos lagi.
Aku membaca ulang surat-surat lama yang kusimpan. Bahkan surat elektronik sepuluh tahun lalu masih bisa membuatku berlinang. Ternyata waktu tidak bisa membunuh rasa, ia hanya mengarsipkannya. Kadang, kita hanya perlu membuka folder yang tepat.
Di kampus, aku mengajar tentang sistem digital. Tapi dalam hatiku, aku tahu: pesan yang paling menyentuh tidak selalu berasal dari teknologi tercanggih. Kadang, ia datang dari tulisan tangan di kertas murah, atau dari kata sederhana seperti “apa kabar?”
Temanku bilang, “Jangan terlalu berharap dari surat. Lebih baik tak menunggu.” Tapi aku tahu, itu bukan tentang hasilnya. Menunggu itu sendiri adalah proses mencintai, tanpa syarat. Seperti menanam pohon yang mungkin tak akan sempat kita panen.
Aku mencoba menulis surat balasan untuk email yang belum datang. Isinya? “Terima kasih sudah membuatku menunggu.” Karena menunggu surat mengajarkan kita tentang kesabaran, dan diam-diam, tentang iman.
Kadang aku merasa surat yang tak kunjung datang itu seperti cinta tak berbalas. Kita tahu kehadirannya, kita yakini kemungkinan datangnya, tapi entah mengapa, tak juga tiba. Lalu kita belajar menerima, dengan cara paling manusiawi: menangis dalam diam.
Suatu sore, aku duduk di taman kota, membawa laptop. Wifi gratis menyala, notifikasi berdenting. Bukan kabar yang kutunggu, tapi sapaan dari sahabat lama. Seketika, aku lupa surat yang tak datang. Ternyata, hidup selalu punya kejutan, meski tak selalu sesuai agenda kita.
Surat bisa saja datang terlambat. Bisa jadi, kabar yang mestinya dikirim bulan lalu baru muncul minggu depan. Tapi hidup memang begitu: tidak selalu tepat waktu, tapi selalu punya cara.
Aku menulis jurnal harian, dan di setiap halaman, aku beri catatan kecil: “Masih menunggu surat itu.” Seperti mantra, aku berharap kalimat itu mengundang datangnya kabar baik. Walau dalam hati, aku tahu, tak semua mantra bekerja.
Kawanku pernah bilang, “Mungkin surat itu tak datang karena belum waktunya.” Kalimat sederhana itu membuatku terdiam. Barangkali benar. Semesta punya cara merapikan hidup kita, bahkan dengan cara menyembunyikan kabar.
Malam ini, aku membuka laptop tanpa harap. Tapi entah kenapa, jari ini tetap mengecek kotak masuk. Masih kosong. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Hatiku tak lagi berat. Mungkin karena aku mulai belajar menerima ketidakpastian sebagai bagian dari hidup.
Di depan kantor pos, aku melihat seorang wanita membaca surat cetak. Matanya berbinar, sesekali tertawa kecil. Aku hampir ingin menanyakan siapa pengirimnya. Tapi tak perlu. Wajahnya cukup jadi jawaban: surat, betapapun ringkasnya, bisa mengubah hari seseorang.
Kadang, surat yang tidak kita terima justru membentuk kita. Ia menjadi jeda yang mengajarkan kita tentang nilai sebuah harapan. Dan dalam sunyi itu, kita mengenal suara hati sendiri.
Mungkin surat yang kutunggu bukanlah kabar yang diketik dan dikirim melalui sistem. Mungkin ia adalah pesan dari Tuhan, yang datang lewat peristiwa, lewat pertemuan, lewat kesadaran. Bukan sekadar informasi, tapi hikmah.
Maka malam ini, aku menulis satu surat untuk diriku sendiri. Isinya: “Kau telah menunggu dengan baik. Tak apa jika surat itu tak datang. Yang penting, kau tetap membuka jendela, tetap menaruh cermin kecil, dan tetap percaya pada cahaya pagi yang akan datang.”