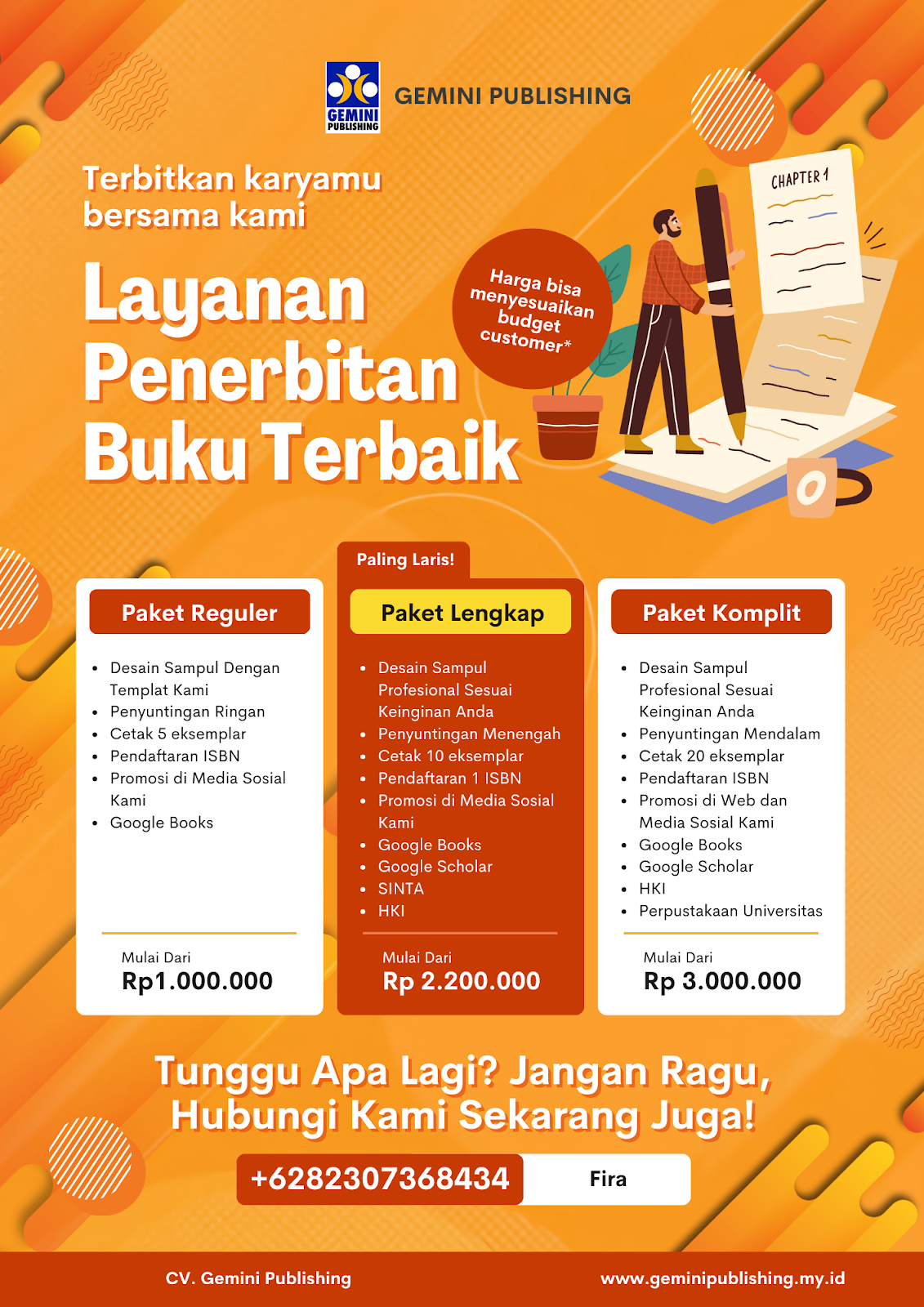Saya masih ingat betu, setiap kali masuk kantor pemerintahan, yang pertama kali menatap kita bukan pegawainya. Bukan juga resepsionisnya. Tapi foto presiden dan wakil presiden yang dipajang gagah di dinding. Kadang ditemani gubernur atau bupati setempat. Rasanya seperti ada yang mengawasi dari atas, meski tak pernah benar-benar menegur kalau kita telat kerja.
Kebiasaan itu sudah berlangsung lama. Dari zaman saya kecil, setiap sekolah selalu punya sudut wajib: papan tulis, lambang Garuda, dan foto presiden serta wakilnya. Ada semacam paket lengkap. Tidak bisa salah satu hilang. Kalau salah satunya tidak ada, seperti rumah tanpa atap. Seperti sayur tanpa garam.
Pertanyaan saya sederhana: untuk apa sebenarnya foto itu? Apakah benar ada hubungannya dengan kinerja? Apakah pegawai jadi lebih rajin kalau tiap hari dipandangi wajah presiden? Atau malah tidak ada bedanya, hanya jadi formalitas belaka. Sekadar dekorasi dinding biar tidak kosong.
Saya pernah iseng bertanya kepada seorang pejabat teras di daerah. Kenapa selalu ada foto bupati di setiap ruangannya? Jawabannya singkat: “Tradisi.” Dia tidak tahu apakah ada dasar hukum yang mewajibkan. Tapi katanya, kalau tidak dipasang, bisa dianggap tidak loyal. Bisa dipertanyakan kesetiaannya pada pimpinan.
Di sisi lain, ada pegawai yang melihat foto itu seperti pengingat. Katanya, setiap kali melihat wajah presiden, ia merasa sedang bekerja untuk negara. Untuk rakyat. Jadi, sedikit banyak ada efek psikologis. Meski, kalau kita jujur, sering kali yang bekerja justru lebih dipengaruhi oleh gaji, tunjangan, dan atasan langsung.
Saya pernah masuk ke sebuah kantor swasta yang besar. Tidak ada foto presiden di sana. Yang ada hanya foto pendiri perusahaan. Bahkan fotonya dibuat lebih besar dari lukisan-lukisan yang lain. Apakah ini salah? Tidak. Bagi mereka, simbol pemersatu bukan presiden, melainkan sang pendiri yang berjasa besar mendirikan perusahaan.
Di negara lain, tradisi ini tidak selalu sama. Di Amerika Serikat, misalnya. Tidak semua kantor pemerintah memasang foto presiden. Yang lebih sering dipasang justru bendera. Bintang-bintang dan garis merah putih itu yang dianggap simbol paling penting. Foto presiden? Tidak wajib. Bahkan di beberapa kantor kecil, tidak pernah ada.
Di Taiwan, tradisi semacam itu hampir tidak ditemukan. Pegawai lebih sibuk menunduk pada pekerjaannya daripada menatap foto pemimpinnya. Bagi mereka, simbol penghormatan ada pada etos kerja. Mereka menunjukkan nasionalisme dengan produktivitas. Bukan dengan foto. Itu sebabnya, kantor mereka sering kosong dari gambar pemimpin.
Lain lagi di Korea Utara. Di sana foto pemimpin bukan sekadar pajangan. Melainkan kewajiban. Bahkan harus dijaga kebersihannya setiap hari. Warga bisa dianggap tidak hormat kalau foto pemimpin berdebu. Ini sudah masuk ke ranah ideologi. Pemimpin menjadi semacam dewa. Beda jauh dengan di sini, meski kadang-kadang kita menirunya dalam versi lebih halus.
Kalau di Indonesia, keberadaan foto presiden seolah jadi aturan tak tertulis. Saya coba telusuri. Ada beberapa surat edaran dari kementerian dalam negeri dan sekretariat negara soal tata cara penggunaan lambang negara. Tapi soal foto presiden? Tidak ada aturan eksplisit yang mengatur. Artinya, ini lebih pada kebiasaan daripada hukum.
Saya teringat pada era Presiden Soeharto. Foto beliau seperti bagian dari paket wajib pembangunan. Di sekolah, kantor, bahkan pos ronda pun kadang ada. Setelah reformasi, kebiasaan itu tetap bertahan. Berganti presiden, berganti foto. Tapi intinya sama: wajah pemimpin tetap harus menatap kita dari dinding.
Pernah juga ada cerita menarik. Ada kantor daerah yang telat mengganti foto presiden baru. Masih terpajang wajah presiden sebelumnya. Lalu datang inspeksi. Pegawai kantor itu ditegur. Katanya, itu dianggap tidak menghormati presiden baru. Padahal mungkin hanya karena lupa atau belum sempat mengganti.
Sebenarnya, apa hubungannya foto dengan nasionalisme? Kalau saya perhatikan, lebih banyak simbolisme daripada substansi. Rasa cinta tanah air tidak otomatis tumbuh hanya dengan menatap foto. Ia tumbuh dari kebijakan yang adil, pelayanan yang baik, dan kesejahteraan yang nyata. Foto hanya hiasan. Nasionalisme butuh isi.
Meski begitu, saya tidak bisa menolak bahwa simbol tetap punya peran. Foto presiden bisa jadi simbol legitimasi. Seperti ingin mengatakan: kantor ini resmi, sah, dan berada di bawah negara. Simbol semacam ini memang penting, apalagi di daerah yang jauh. Kadang foto itu menjadi bukti nyata bahwa negara hadir.
Ada juga yang bilang, memasang foto presiden itu bagian dari budaya timur. Budaya menghormati pemimpin. Di Barat, hubungan rakyat dan pemimpin lebih egaliter. Foto bukan hal penting. Tapi di sini, penghormatan harus ditunjukkan dengan cara-cara simbolis. Termasuk dengan foto yang dipajang di dinding.
Saya ingat pernah masuk ke sebuah kantor desa di satu daerah. Fotonya lusuh, warnanya pudar, bingkainya berkarat. Tapi pegawai bilang, foto itu sakral. Tidak boleh dilepas meski sudah usang. Mereka lebih memilih membiarkannya begitu daripada dianggap kurang hormat. Saya tersenyum. Simbol bisa lebih kuat dari fungsi.
Namun, kadang simbol bisa membingungkan. Ada kantor yang menempel foto presiden dan wakil presiden, tapi lupa bendera merah putih. Ada juga yang menaruh foto presiden lama berdampingan dengan presiden baru. Jadi semacam galeri. Orang luar yang masuk jadi bingung, ini kantor atau museum?
Bagi saya pribadi, melihat foto presiden tidak pernah menambah semangat kerja. Tapi saya tahu, bagi sebagian orang, itu penting. Sama seperti kita menaruh foto keluarga di meja kerja. Tidak semua merasa perlu. Tapi bagi yang merasa perlu, ada energi psikologis yang lahir dari tatapan wajah di foto itu.
Di negara berkembang lain, kebiasaan ini juga ada. Di Filipina, foto presiden sering dipajang di kantor pemerintah. Di India, lebih banyak patung atau gambar tokoh besar. Gandhi, misalnya. Jadi, pola ini bukan hanya milik kita. Tapi setiap negara punya variasinya sendiri.
Kalau ditanya soal dasar hukum, jawabannya: tidak ada aturan khusus. Yang ada hanya surat edaran atau kebiasaan administratif. Jadi, sebenarnya tidak wajib. Kalau ada kantor pemerintah yang tidak memasang foto presiden, itu tidak melanggar hukum. Hanya saja, konsekuensi sosialnya bisa dianggap kurang hormat.
Pernah ada aktivis yang menolak memasang foto presiden di kantornya. Alasannya: presiden bukan simbol negara, melainkan pejabat politik yang bisa berganti. Simbol negara adalah bendera dan Garuda. Argumen ini masuk akal. Tapi tentu saja, di level praktik, orang tetap memilih aman. Lebih baik pasang foto daripada ribut.
Pertanyaannya, sampai kapan kebiasaan ini bertahan? Apakah kelak, di era digital, foto presiden di dinding akan diganti dengan layar elektronik? Yang bisa otomatis berganti saat presidennya berganti. Atau malah hilang sama sekali, diganti dengan QR code yang mengarahkan ke profil resmi presiden di website.
Di balik semua itu, saya tetap melihat ada sisi baik. Foto presiden di dinding memberi pesan: kita punya pemimpin. Entah suka atau tidak suka, itu adalah pemimpin kita. Seperti halnya di keluarga, kadang kita tidak selalu setuju dengan orang tua. Tapi tetap harus mengakui bahwa merekalah yang memimpin rumah tangga.
Sebagian orang mungkin bosan dengan simbol. Mereka lebih ingin melihat kerja nyata. Jalan yang mulus, pelayanan cepat, birokrasi efisien. Foto tidak bisa memperbaiki jalan rusak. Tidak bisa mempercepat izin. Tidak bisa menurunkan harga kebutuhan pokok. Jadi, jangan sampai simbol lebih kuat dari substansi.
Tapi saya juga paham. Dalam politik, simbol itu penting. Kadang lebih penting daripada substansi. Orang rela mengeluarkan uang besar hanya untuk membuat baliho besar. Padahal isinya hanya foto senyum. Tanpa program. Itu karena simbol bisa menciptakan rasa hadir. Bisa menumbuhkan loyalitas. Bisa memberi ilusi kehadiran.
Apakah kita harus terus melestarikan kebiasaan ini? Mungkin iya. Tidak ada salahnya. Selama tidak menganggap foto sebagai sumber segala semangat. Biarlah ia jadi pajangan. Tapi jangan lupa, isi dari kerja lebih penting daripada bingkai di dinding.
Kalau memang ingin menunjukkan loyalitas pada negara, sebaiknya ditunjukkan lewat pelayanan yang baik. Bukan lewat foto. Kalau ingin menunjukkan nasionalisme, lakukan lewat kerja yang bermanfaat bagi rakyat. Foto hanya pelengkap. Kerja nyata adalah inti.
Saya teringat ucapan seorang PNS yang sudah senior. Katanya, ia tidak peduli siapa presidennya. Fotonya boleh berganti. Tapi pekerjaannya tetap sama. Pelayanan pada rakyat. Mungkin inilah kunci sebenarnya. Foto boleh jadi simbol, tapi isi dari kerja tetap yang menentukan.
Kalau begitu, apakah ada gunanya kita memperdebatkan soal foto? Bagi sebagian orang, penting. Bagi sebagian lain, tidak. Tapi saya memilih melihatnya sebagai bagian dari budaya. Budaya menghormati pemimpin. Selama tidak berlebihan, tidak ada yang salah.
Toh, di ruang tamu kita pun sering ada foto keluarga. Itu tidak menjamin keluarga selalu harmonis. Tapi tetap saja kita pasang. Karena simbol itu penting, meski bukan segalanya. Begitu juga dengan foto presiden di kantor. Penting, tapi bukan penentu segalanya.
Pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan foto. Yang kita butuhkan adalah kepemimpinan yang nyata. Pemimpin yang hadir lewat kebijakan. Pemimpin yang hadir lewat solusi. Foto hanya memberi wajah. Tapi kepemimpinan memberi arah.
Dan arah itulah yang sesungguhnya kita cari. Di balik semua bingkai di dinding. Di balik semua simbol yang kita jaga. Kita tetap menunggu kerja nyata. Dari siapa pun yang wajahnya sedang kita pandang di dinding itu.